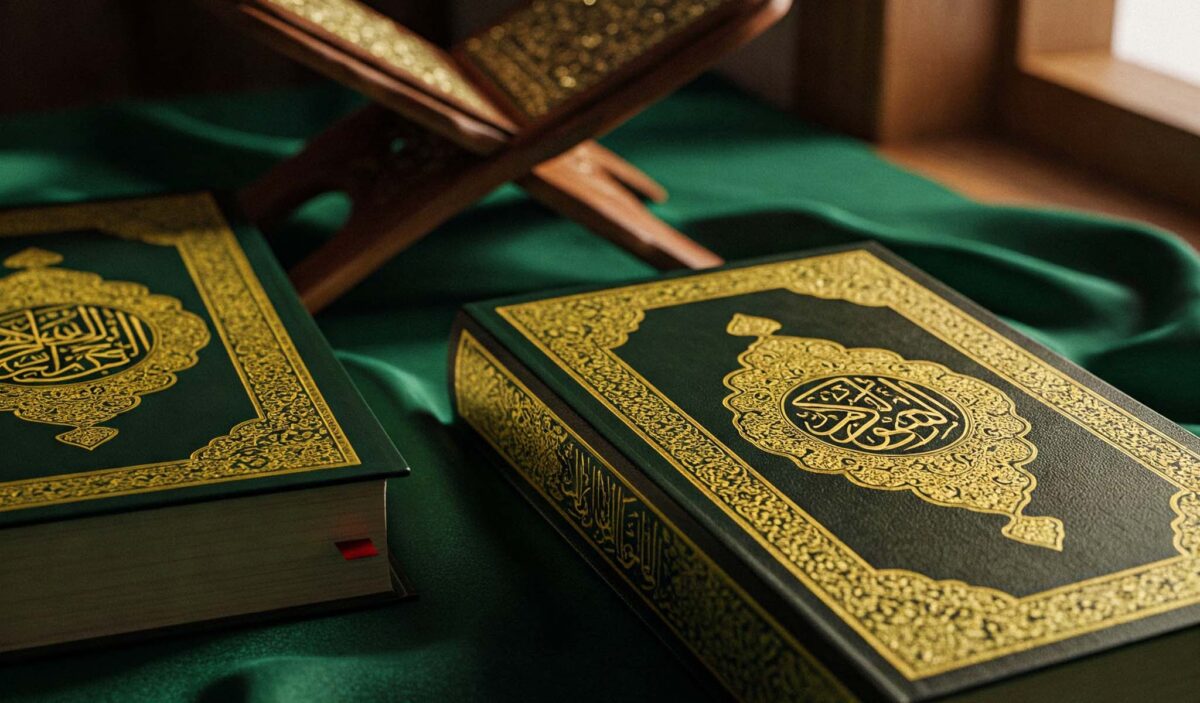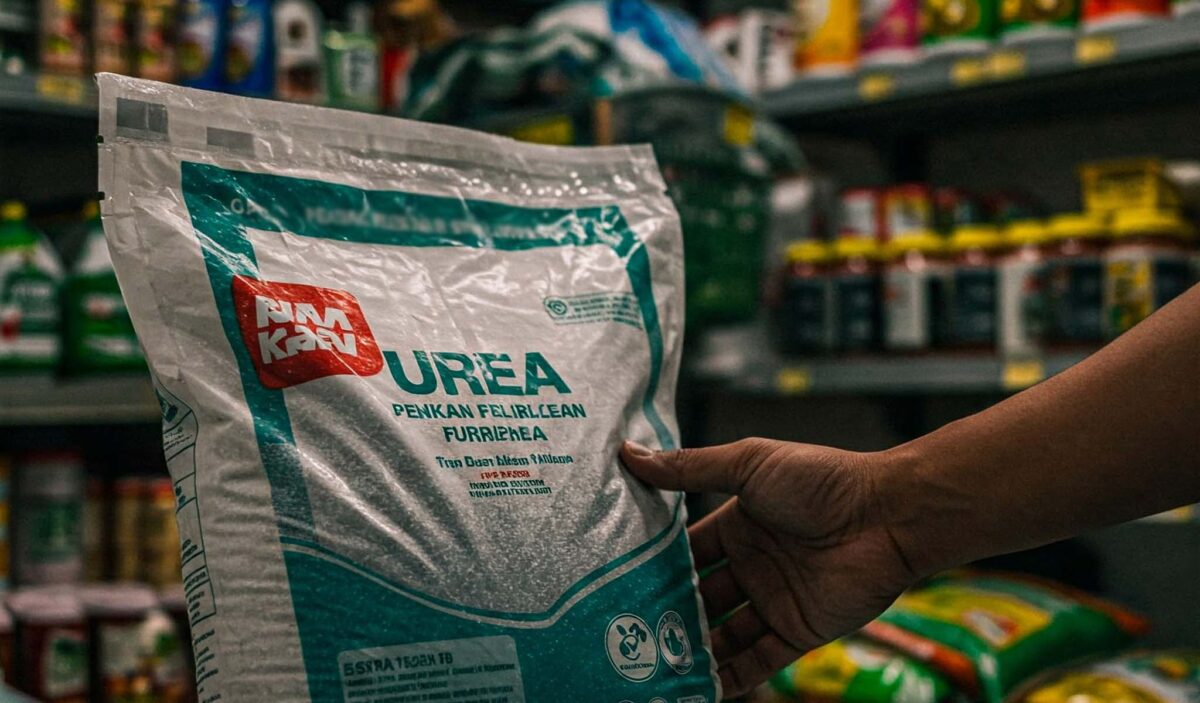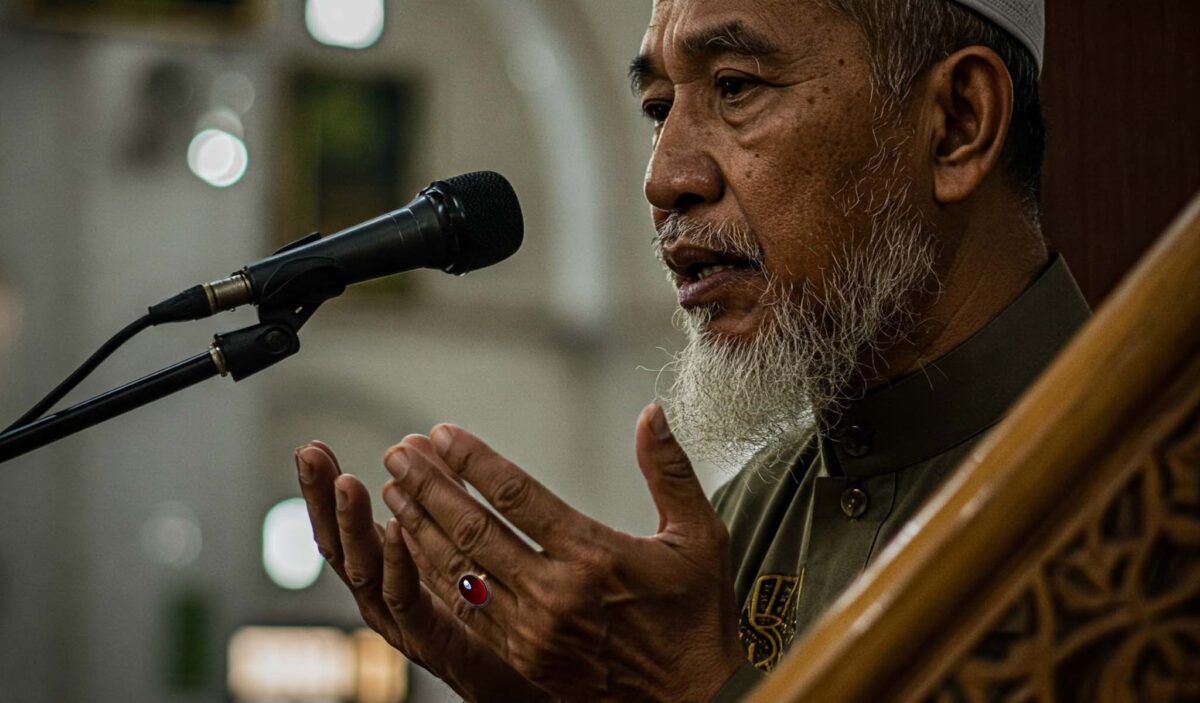Assalamualaikum
Deskripsi Masalah:
Kebanyakan umat Islam terutama masyarakat awam masih merasa timbul tanda tanya terhadap suatu berita yang menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup,Pasalnya karena ada seseorang pernah sowan kepada salah satu Kiyai yang punya karomah ia berkomunikasi dengan orang sudah meninggal ( Waliyyullah) dengan mengucapkan salam terlebih duhulu Kepada orang yang meninggal lalu membaca fatihah dikhususkan kepadanya ( orang yang meninggal). Tapi yang sowan tidak melihatnya . Demikian juga ada yang mengatakan bahwa di dalam kuburan bersemayam seorang waliyyullah padahal sebelumnya tidak ada orang yang tahu.
Pertanyaan:
1. Apa ada keterangan yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup?
2. Apakah dapat dibenarkan ucapan orang yang mengatakan bahwa di dalam kuburan ini bersemayam seorang waliyyullah?
3. Bagaimana hukumnya bertawasul kepada orang yang diduga seorang waliyyullah?
Waalaikumsalam salam
Jawaban
1. Apakah orang yang meninggal bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup?
Dalam Al-Qur’an dan Hadis, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang meninggal dapat berkomunikasi langsung dengan orang yang masih hidup. Namun, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan kemungkinan interaksi antara ruh orang hidup dan ruh orang meninggal, khususnya dalam mimpi. Firman Allah dalam QS. Az-Zumar [39]: 42
“يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Ayat ini menunjukkan bahwa ruh seseorang dapat bertemu dalam mimpi:
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya…”
Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan bahwa ruh orang hidup dan ruh orang mati dapat bertemu dalam mimpi dan saling mengenal. Namun, ini adalah bentuk pertemuan ruh dan bukan komunikasi fisik langsung.
2. Benarkah klaim bahwa di kuburan tertentu bersemayam seorang waliyyullah?
Tidak ada dalil tegas dalam Al-Qur’an atau Hadis yang menyebutkan keberadaan waliyyullah di kuburan tertentu tanpa bukti yang jelas. Namun, ziarah kubur yang dilakukan untuk mendoakan ahli kubur adalah amalan sunnah. Mengklaim bahwa seseorang adalah waliyyullah harus berdasarkan bukti yang kuat, seperti kesalehan hidupnya yang masyhur di masyarakat. Dalam kitab Tuhfah At-Tathrib, disebutkan pentingnya mengetahui lokasi makam para orang saleh untuk ziarah dan menghormatinya, tetapi klaim tanpa bukti tidak dianjurkan.
3. Bagaimana hukum bertawasul kepada waliyyullah?
Bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang saleh, atau waliyyullah yang sudah meninggal adalah hal yang disepakati sebagai bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan hukumnya sunnah dengan syarat niat bertawasul adalah memohon kepada Allah melalui kedudukan mereka di sisi-Nya. Dalilnya terdapat dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 35:
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (perantara) kepada-Nya…”
Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi oleh Imam As-Suyuthi disebutkan bahwa bertawasul adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, dalam Tabaqat Al-Kubra karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwa karomah wali mencakup kemampuan memberi manfaat atau syafaat dengan izin Allah.
Kesimpulan:
a).Komunikasi semacam ini tidak terjadi secara fisik, melainkan dalam bentuk mimpi atau pertemuan ruh yang diizinkan Allah.
b).Pernyataan bahwa di suatu kuburan bersemayam wali harus didasarkan pada riwayat atau bukti yang kuat, bukan hanya dugaan.
c). Bertawasul kepada waliyyullah diperbolehkan dan merupakan sunnah, asalkan tidak menimbulkan keyakinan syirik bahwa wali tersebut memiliki kekuatan selain dari Allah.
Catatan Penting:
Karomah: Keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-Nya sebagai tanda kedekatan mereka dengan Allah.
Penting untuk tetap berada dalam koridor tauhid, tidak menisbahkan kekuatan atau kemampuan kepada wali selain atas kehendak Allah.
Referensi Utama:
QS. Az-Zumar [39]: 42
QS. Al-Ma’idah [5]: 35
Ar-Ruh karya Ibn Qayyim
Al-Hawi lil Fatawi karya Imam As-Suyuthi
Tuhfah At-Tathrib dan Kitab lainnya sebagaimana ibarat berikut:
جامع كرامات الأولياء، صفحة ١٤
المسألة الثالثة: وهل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟
شواهد هذه المسألة وأدلتها كثيرة من أن يحصيها إلا الله تعالى والحس والواقع من أعدل الشُهود بها فتلاقى أرواح الأحياء والأموات كما تلاقى أرواح الأحياء وقد قال تعالى: “يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”. قال أبو عبد الله بن مندة حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن حسين الحاراني حدثنا جدي أحمد بن شُعَيْبٍ حدثنا موسى بن عين عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتسألون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا عبد الله بن سُلَيْمَانَ حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وفي قوله تعالى “والَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا” (الزمر ٣٩:٤٩) قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعرفان قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الآية (الروح ٢٠).
المطلب الثاني في أنواع الكرامات. قال النووي في طبقات الكبرى للكرامات أنواع النوع الأول إحياء الموتى إلى أن قال النوع الثاني: (من الكرامة) كلام الموتى وهو أكثر من النوع قبله وروي مثله عن أبي سعيد الخراز ثم عن الشيخ عبد القادر وعن جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الإمام الوالد يعني والده الإمام تقي الدين الشبكي رحمه الله. الثالث: أن جماعة من أئمة الشريعة نصوا على أن من كرامة الولي أنه يرى النبي ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب، وممن نص على ذلك من أئمة الشافعية الغزالي والبارزي والتاج بن السبكي والعفيف اليافعي ومن أئمة المالكية القرطبي وابن أبي جمرة وابن الحاج في المدخل وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروا ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي هذا الحديث باطل فقال الفقيه ومن أين لك هذا فقال هذا النبي واقف على رأسك يقول إني لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرآه وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي لو حجبني عن النبي طرفة عين ما عدت نفسي مع المسلمين فإذا كان هذا حال الأولياء مع النبي فعيسى النبي أولى بذلك أن يجتمع به في أي وقت شاء ويأخذ عنه ما أراد من أحكام شريعته من غير حاجة إلى اجتهاد ولا تقليد لحفاظ الحديث”
“والحاوي للفتاوي للسيوطي ٢/١٥٤”.
“واختلف أهل العلم هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا فكان الإمام أبو بكر بن فورق رحمه الله تعالى يقول لا يجوز ذلك لأنه يسلب الخوف ويوجب له الأمان وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول بجوازه وهو الذي تؤثره ونقول به وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون كل ولي يعلم أنه ولي واجب بشكل واجب أنه ولي ولكن يجوز أن يعلم بعضهم ذلك كما يجوز أن يعلم بعضهم فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها”.
Masalah Ketiga: Apakah ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang telah meninggal bisa saling bertemu atau tidak?
Dalil-dalil dan bukti-bukti terkait masalah ini sangat banyak, bahkan hanya Allah yang mampu menghitungnya. Kenyataan dan fakta menjadi saksi paling adil atas adanya pertemuan antara ruh orang yang hidup dan ruh orang yang telah meninggal, sebagaimana ruh-ruh orang yang hidup dapat saling bertemu. Allah Ta’ala berfirman:
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Az-Zumar [39]: 42).
Abu Abdullah bin Mandah meriwayatkan: “Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Husain al-Harani telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Kakekku Ahmad bin Syu’aib telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Ayyun telah menceritakan kepada kami dari Mutarrif dari Ja’far bin Abi al-Mughirah dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, ia berkata: Aku mendengar bahwa ruh orang yang hidup dan ruh orang yang meninggal bertemu dalam mimpi, lalu mereka saling bertanya satu sama lain. Maka Allah menahan ruh orang yang telah meninggal dan mengembalikan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya.”
Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya berkata: “Abdullah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath telah menceritakan kepada kami dari al-Suddi tentang firman Allah Ta’ala: ‘Dan yang belum mati di waktu tidurnya’ (QS. Az-Zumar [39]: 42). Ia berkata: Allah mencabut ruh seseorang di saat tidurnya, lalu ruh orang yang hidup bertemu dengan ruh orang yang mati. Mereka saling berbincang dan saling mengenal. Kemudian ruh orang yang hidup dikembalikan ke jasadnya di dunia hingga sisa ajalnya, sedangkan ruh orang yang telah meninggal ingin kembali ke jasadnya, tetapi tertahan.” Ini adalah salah satu pendapat tentang ayat tersebut. (Kitab al-Ruh, hal. 20).
Bagian Kedua: Tentang Jenis-jenis Karomah.
Imam al-Nawawi dalam Tabaqat al-Kubra menyebutkan bahwa karomah memiliki beberapa jenis:
1. Jenis pertama adalah menghidupkan orang yang telah meninggal.
2. Jenis kedua adalah (dari karomah) berbicara dengan orang yang telah meninggal. Jenis ini lebih sering terjadi dibandingkan jenis sebelumnya. Hal ini diriwayatkan dari Abu Said al-Kharraz, kemudian dari Syekh Abdul Qadir, dan sekelompok ulama lainnya hingga sebagian guru besar Syekh Imam ayahnya, yakni Imam Taqiyuddin al-Subki, rahimahullah.
3. Jenis ketiga adalah sebagian imam syariat menegaskan bahwa salah satu karomah seorang wali adalah ia dapat melihat Nabi Muhammad SAW, bertemu dengannya dalam keadaan terjaga, dan mengambil darinya ilmu pengetahuan serta anugerah yang telah dibagi untuknya.
Di antara yang menyebutkan hal ini dari kalangan ulama mazhab Syafi’i adalah Imam al-Ghazali, al-Barizi, Tajuddin al-Subki, dan al-‘Afif al-Yafi’i. Dari kalangan ulama mazhab Maliki adalah Imam al-Qurthubi, Ibn Abi Jamrah, dan Ibn al-Hajj dalam kitab al-Madkhal.
Diriwayatkan bahwa salah seorang wali menghadiri majelis seorang faqih. Sang faqih meriwayatkan sebuah hadis, lalu wali tersebut berkata: “Hadis ini batil.” Sang faqih bertanya: “Dari mana kamu tahu itu?” Ia menjawab: “Ini Nabi SAW berdiri di belakangmu dan berkata: ‘Aku tidak pernah mengatakan hadis ini.’” Lalu sang wali menunjukkan kepada faqih tersebut sehingga ia pun melihat Nabi SAW.
Syekh Abu Hasan al-Syadzili berkata: “Seandainya aku terhalang dari Nabi SAW walau sekejap mata, aku tidak akan menganggap diriku sebagai seorang Muslim.” Jika ini adalah keadaan para wali dengan Nabi SAW, maka Nabi Isa AS tentu lebih berhak bertemu dengannya kapan pun ia mau, mengambil darinya hukum-hukum syariat tanpa perlu ijtihad atau taqlid kepada para hafiz hadis. (Kitab al-Hawi lil Fatawi oleh Imam al-Suyuthi, jilid 2, hal. 154).
Perbedaan Pendapat tentang Apakah Seorang Wali Mengetahui Dirinya sebagai Wali atau Tidak.
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Bakr bin Furak, rahimahullah, mengatakan: “Tidak boleh bagi seorang wali untuk mengetahui bahwa dirinya adalah wali karena hal itu dapat menghilangkan rasa takut dan menyebabkan rasa aman.”
Sedangkan Ustadz Abu Ali al-Daqqaq, rahimahullah, berpendapat: “Hal itu boleh diketahui.” Pendapat ini yang diunggulkan, dan kami mengikutinya. Namun, hal tersebut tidak wajib bagi semua wali sehingga setiap wali harus mengetahui dirinya sebagai wali. Hal ini hanya terjadi pada sebagian wali, sebagaimana mungkin sebagian mereka mengetahuinya. Jika seorang wali mengetahui bahwa dirinya adalah wali, maka pengetahuan tersebut adalah karomah baginya yang menjadi keistimewaannya.
“الرسالة التفسيرية (٣٥٤)”.
“وذكر ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة وقد اشتهر أن قبرا قريبا من أريحا وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر موسى وعنده كثيب أحمر وطريق وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى”.
“Ar-Risalah At-Tafsiriyah (354)”
Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab Shahih-nya bahwa makam Nabi Musa berada di Madyan, antara Madinah dan Baitul Maqdis. Pernyataan ini dibantah oleh Al-Hafizh Dhiyauddin Al-Maqdisi. Ia mengatakan bahwa pendapat tersebut perlu ditinjau ulang dan mendukung argumennya dengan hadits ini. Al-Maqdisi menyatakan, ‘Madyan tidak dekat dengan Baitul Maqdis maupun dengan tanah suci. Telah masyhur bahwa ada sebuah makam dekat Ariha (Jericho), yang termasuk tanah suci, sering diziarahi dan dikatakan sebagai makam Nabi Musa. Di sana terdapat bukit kecil berwarna merah dan sebuah jalan. Beberapa orang yang telah menziarahinya menceritakan hal tersebut kepada kami.’ Selesai.
دقائق الأخبار فى باب الحادي عشر فى ذكر نداء الروح بعد الخروج ص١١
وعلى هذا حكاية أبي قلابة رضي الله عنه وهى ماروى أنه رأى فى المنام كان القبور قد انشقت وأمواتها قد خرجوا منها وقعدوا على شفير القبور وكان بين يدي كل واحد منهم طبق من نور ورأى فيما بينهم رجلا من جيرانهم ولم ير من بين يديه شيأ فسألته فقلت مالي لاأدري بين يديك نور فقال الميت إن لهؤلاء أولادا وأصدقاء يهدون إليهم خيرا ويتصدقون لأجلهم وهذالنور ممايهدونه إليهم وكان لي إبن غير صالح ولايدعو لي ولايتصدق لأجلي ولهذا لانور لي وأنا خجل بين جيراني فلما انتبة أبو قلابة دعا إبنه وأخبره بما رأى فقال ابن أنا تبت على يدك فلاأعود الى ماكنت عليه أبدا فاستغل بالطاعة والدعاء والتصدق عن أبيه لأجله فلما مضى عليه زمان رأى أبو قلابة مرة أخرى فى منامه تلك المقبرة على حالها ورأى نور بين يدي ذلك الجل أضوأ من الشمس أكثر من نور أصحابه فقال لي ياأباقلابة جزاك الله خيرا فقد نجوت من خجلة الجيران
Disebutkan dalam kitab Daqoiqul Akhbar pada bab 11 yang menerangkan tentang seruan ruh setelah keluar
Dan atas dasar ini ada sebuah HIKAYAT dari Abi qilabah ra. dan hikayat itu menerangkan bahwa di dalam mimpi Abi Qilabah ada suatu kejadian seakan-akan suatu perkuburan telah terbelah lalu keluarlah semau ahli kubur darinya. Mereka duduk-duduk di tepi kubur, sedangkan di hadapan masing-masing mereka terdapat sebuah talam dari cahaya, dan Abu Qilabah melihat bahwa salah satu di antara ahli kubur itu terdapat seorang yang tidak cahaya sedikitpun di mukanya ( wajahnya) . Lalu dia( Abu Qilabah ) bertanya kepadanya : “Apa sebabnya tidak aku lihat di mukamu secerah cahayapun?” maka mayat tersebut menjawab : “Sesungguhnya mereka-mereak itu yang bercahaya adalah (tetangga ku ) mempunyai anak dan sahabat-sahabat yang sama-sama menghadiahkan amal kebaikan dan shadaqah bagi mereka. Dan cahaya itulah adalah sebagai bukti dari hadiah-hadiah mereka. Sedangkan saya mempunyai anak yang tholeh ( durhaka) ia tidak bershadaqah untuk diriku, maka dari itu tiada secercahpun cahaya yang aku miliki, hingga aku merasa malu kepada tetanggaku.” Ketika Abi Qilabah terbangun maka dia memanggil anak dari mayat yang diimpikan tersebut dan menceritakan kepdanya tentang apa yang dilihatnya dalam mimpi ( bertemu dengan ahli kubur ) Maka anak tersebut berkata : “Aku bertaubat di mukamu dan tidaklah aku akan kembali kepada perbuatanku yang lalu untuk selama-lamanya.” Maka anak tersebut mulai menyibukkan diri dengan semua ketaatan, dan berdoa serta bershadaqah demi ayahnya. Ketika selang beberapa waktu Abi Qilabah melihat perkuburan itu yang kedua kalinya dalam mimpi, maka terlihat olehnya nur di muka mayit tersebut yang lebih terang dari cahaya matahari dan lebih banyak dari nur para tetangganya, seraya mayat tersebut berkata : “Wahai Abi Qilabah, mudah-mudahan Allah SWT. membalas kebaikan bagimu karena aku telah selamat dari rasa malu di antara tetangga-tetanggaku.
“طرح التثريب ص٣١٨/٤
الثامنة الكثيب بالتاء المثلة قطعة من الرمـل مستطيلة محدودة سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّهُ انصبَّ في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها، وقد ذكر النبي لقبر السيد موسى علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم التل قال: ما رأيت استحباب الدعاء أسرع منه عند هذا القبر، وحدّثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرميني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئاً فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال: يولد لك أربعة أولاد فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقرّبها فقال: تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد انتهى وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينَا وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه عليهم السلام أيضاً مظنون بمنامات وأنحوها”
“Tuhfah At-Tathrib, hal. 318/4”
_Poin kedelapan: ‘Katsib’ dengan huruf ta’ adalah gundukan pasir memanjang yang terbatas. Dinamakan demikian karena pasir tersebut mengalir ke suatu tempat dan berkumpul di sana. Dari situ disunnahkan untuk mengetahui makam orang-orang saleh guna menziarahinya dan menunaikan haknya. Nabi telah memberikan tanda mengenai makam Nabi Musa, yang sesuai dengan makam yang kini masyhur di kalangan masyarakat sebagai makam beliau. Tampaknya tempat tersebut adalah lokasi yang ditunjukkan Nabi ﷺ. Hal ini diperkuat dengan kisah-kisah dan mimpi-mimpi. Al-Hafizh Adh-Dhiya’ berkata: ‘Syaikh Salim At-Til menceritakan kepadaku bahwa ia tidak pernah melihat doa yang lebih cepat terkabul dibandingkan di makam ini.’
Syaikh Abdullah bin Yunus, yang dikenal dengan sebutan Al-Armini, menceritakan bahwa ia pernah mengunjungi makam tersebut. Ia tidur di sana dan bermimpi melihat sebuah kubah dengan seseorang berkulit sawo matang. Ia menyapanya dan bertanya, ‘Apakah engkau Musa, Kalimullah (yang diajak bicara oleh Allah) atau Nabi Allah?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Lalu saya berkata, ‘Katakanlah sesuatu kepadaku.’ Ia mengisyaratkan dengan empat jarinya yang panjang. Ketika saya terbangun, saya tidak memahami maksudnya. Saya pun menceritakannya kepada Syaikh Dhiyaa’. Ia berkata, ‘Akan lahir bagimu empat orang anak.’ Saya berkata, ‘Saya telah menikahi seorang wanita, tetapi belum berhubungan dengannya.’ Ia berkata, ‘Itu akan terjadi dengan wanita lain.’ Saya kemudian menikahi wanita lain dan memiliki empat anak darinya. Selesai._
Tidak ada makam para nabi yang benar-benar pasti kecuali makam Nabi kita ﷺ. Adapun makam Nabi Musa hanya bersifat dugaan berdasarkan tanda dalam hadits. Sedangkan makam Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya juga hanya bersifat dugaan berdasarkan mimpi-mimpi dan hal serupa.
طرح التثريب ص ٣١٩/٤
(سُئِلَ) عمن أسلم وأبواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعو لوالديه بالرحمة أم لا؟ (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ونحوهما وإلا فلا يجوز ذلك لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم من والديه على سبيل الإيهام فيدخل أبواه في ذلك إن كانا أسلمّا.
Tahrir at-Tathrib (hal. 319, jilid 4):
(Pertanyaan): Seorang yang masuk Islam sedangkan kedua orang tuanya masih kafir, lalu setelah keduanya meninggal ia ragu apakah keduanya telah masuk Islam atau tidak. Apakah ia boleh mendoakan rahmat untuk kedua orang tuanya?
(Jawaban): Jika kuat dugaan bahwa keduanya telah masuk Islam, maka diperbolehkan baginya untuk mendoakan ampunan, rahmat, dan sebagainya untuk mereka. Namun, jika tidak ada dugaan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi, dianjurkan baginya untuk berdoa dengan lafaz yang mencakup setiap orang tua yang masuk Islam secara umum, sehingga kedua orang tuanya termasuk dalam doa tersebut jika memang mereka telah masuk Islam.
نهاية الرملي ٢/٢٧٠
(فائدة): زيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابها أو لنحو دعاء فتسن لكل مسلم أو للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برزخهم تصرفات وبركات لا يحصى مَدَدُها أو لأداء حق كصديق ووالد لخبر: من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة وفي رواية غفر له وكتب له براءة من النار أو رحمة وتأنيس لما روي: أنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان أحبه في الدنيا اهـ إيهاب.
Nihayah ar-Ramli (jilid 2, hal. 270):
(Faedah): Ziarah kubur bisa dilakukan dengan beberapa tujuan:
1. Untuk sekadar mengingat kematian dan akhirat, yang bisa dilakukan hanya dengan melihat kuburan tanpa mengenal pemiliknya.
2. Untuk mendoakan mayit, yang disunnahkan bagi setiap muslim.
3. Untuk mencari keberkahan, yang disunnahkan dilakukan terhadap kuburan orang-orang saleh, karena mereka memiliki pengaruh dan keberkahan di alam barzakh yang tidak terhitung.
4. Untuk menunaikan hak terhadap teman atau orang tua, berdasarkan hadis: “Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, maka ia seperti telah melaksanakan haji.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Dosa-dosanya diampuni, ia ditulis sebagai orang yang terbebas dari neraka, dan mendapatkan rahmat.”
5. Untuk menghibur mayit, sebagaimana diriwayatkan bahwa keadaan mayit di kuburnya paling menyenangkan saat diziarahi oleh orang yang dicintainya di dunia
بغية المسترشدين (٢٠١)
(فائدة): رجل مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهل يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً؟ أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله
تعالى اهـ.
Bughyah al-Mustarsyidin (hal. 201):
(Faedah): Seorang lelaki melewati pemakaman, lalu ia membaca Surah al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya untuk penghuni kubur tersebut. Apakah pahala itu terbagi atau masing-masing penghuni kubur mendapatkan pahala utuh? Ibn Hajar menjawab bahwa sebagian ulama memberi fatwa bahwa setiap penghuni kubur mendapatkan pahala yang utuh, dan hal ini sesuai dengan keluasan rahmat Allah Ta’ala.
بغية المسترشدين ص : ٢٩٧
التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعا كما وردت به السنة الصحيحة،______وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد أطبقوا على طلبه بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى.
“Tawassul kepada para nabi dan wali saat mereka hidup maupun setelah wafat hukumnya mubah secara syariat, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Tawassul kepada para nabi dan orang-orang saleh adalah sesuatu yang disukai dan telah ditetapkan dalam hadits-hadits shahih, bahkan para ulama telah sepakat akan kebolehannya. Bahkan, tawassul dengan amal saleh yang merupakan sesuatu yang bersifat non-fisik telah terbukti kebolehannya, maka tawassul dengan zat (diri) mereka lebih utama.”
بغية المسترشدين ص : ٢٩٧
.أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيئ من دون الله فهو كفر وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار المؤثر في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحا.
“Tawassul kepada para nabi dan wali saat mereka hidup maupun setelah wafat hukumnya mubah secara syariat, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Tawassul kepada para nabi dan orang-orang saleh adalah sesuatu yang disukai dan telah ditetapkan dalam hadits-hadits shahih, bahkan para ulama telah sepakat akan kebolehannya. Bahkan, tawassul dengan amal saleh yang merupakan sesuatu yang bersifat non-fisik telah terbukti kebolehannya, maka tawassul dengan zat (diri) mereka lebih utama.”
بغية المسترشدين ص : ٢٩٧
.أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيئ من دون الله فهو كفر وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار المؤثر في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحا.
“Adapun menjadikan perantara antara hamba dengan Rabb-nya, jika ia memanggil mereka sebagaimana ia memanggil Allah dalam berbagai urusan, serta meyakini bahwa mereka memiliki pengaruh dalam sesuatu tanpa Allah, maka hal tersebut adalah kekufuran. Namun, jika maksudnya adalah bertawassul dengan mereka kepada Allah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan keyakinan bahwa Allah-lah yang memberikan manfaat dan mudarat serta yang berkuasa dalam segala urusan, maka menurut pendapat yang kuat, hal tersebut tidak dianggap kufur meskipun perbuatannya buruk (tidak terpuji).” Wallahu Alam bisshowab.