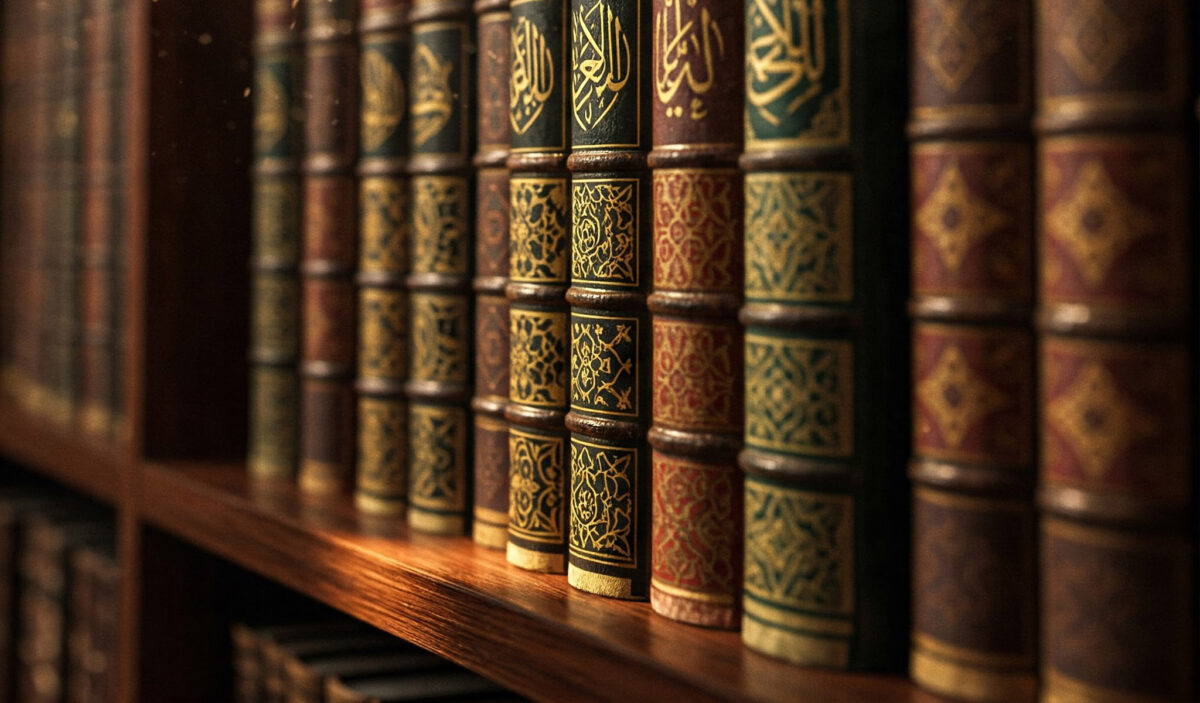Assalamualaikum
Deskripsi:
Seorang Muslim melakukan perjalanan haji dengan berjalan kaki dari rumahnya hingga ke Makkah.Setelah melakukan rukun-rukun haji, seperti diantaranya thawaf, melempar jumroh, dan wukuf diarafah lalu kembali lagi ke kampung halamannya, meskipun terdapat fasilitas kendaraan seperti mobil, kapal, dan pesawat yang dapat mempermudah perjalanan. Perjalanan ini tentu sangat melelahkan dan memerlukan waktu yang lama, tetapi orang tersebut tetap memilih cara ini dengan alasan tertentu, baik karena keyakinan, nazar, atau alasan pribadi lainnya.
Dalam Islam, kemampuan finansial dan fisik menjadi syarat utama bagi seseorang yang wajib menunaikan haji. Maka, muncul pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana hukumnya haji kebaitullah dengan berjalan kaki menurut Madzhab yang empat?
Waalaikum Salam
Jawaban
Hukum Haji ke Baitullah dengan Berjalan Kaki Menurut Empat Mazhab
1. Mazhab Hanafi
Dalam Mazhab Hanafi, seseorang dianggap memiliki kemampuan fisik untuk berhaji jika ia sehat dan mampu bertahan di atas kendaraan. Haji tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu berjalan kaki. Namun, bagi orang yang tinggal dekat Mekah (kurang dari tiga hari perjalanan), ia wajib berhaji meskipun dengan berjalan kaki jika mampu.
2. Mazhab Maliki
Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mampu berjalan kaki ke Mekah, maka ia wajib berhaji meskipun tidak memiliki kendaraan. Bahkan, seorang tunanetra yang mampu berjalan dengan bantuan pemandu tetap wajib berhaji. Namun, jika perjalanan dengan berjalan kaki menimbulkan kesulitan luar biasa yang melampaui kebiasaan, maka haji tidak wajib baginya.
3. Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i menetapkan bahwa seseorang yang tinggal jauh dari Mekah (lebih dari dua marhalah / ±89 km) wajib memiliki kendaraan. Kemampuan berjalan kaki tidak menggugurkan kewajiban memiliki kendaraan. Namun, jika jaraknya kurang dari dua marhalah dan ia mampu berjalan kaki, maka ia wajib berhaji dengan berjalan kaki.
Adapun jika bernadzar atau bersumpah untuk berjalan kaki kebaitullah,( haji) maka ia wajib berjalan kaki, namun jika tidak mampu maka ia wajib membayar kaffarat
4. Mazhab HanbaliMazhab Hanbali menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kendaraan tetapi mampu berjalan kaki atau bekerja di perjalanan tanpa meminta-minta, maka disunnahkan baginya untuk berhaji. Berjalan kaki dianggap menunjukkan kesungguhan dalam ibadah dan keluar dari perbedaan pendapat tentang wajibnya berjalan kaki bagi yang mampu.
Kesimpulan
Menurut Mazhab Maliki, seseorang yang mampu berjalan kaki wajib berhaji meskipun tanpa kendaraan. Sementara dalam Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali, seseorang yang tidak memiliki kendaraan tidak wajib berhaji, kecuali jika jaraknya dekat atau mampu berjalan kaki tanpa kesulitan yang luar biasa.
فقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج.٣ ٢٠٨٢-٢٩٠
٤ – الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج: وهي القدرة على الوصول إلى مكة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران:٩٧/ ٣]، لكن للفقهاء بعض الاختلافات في حدود ووجوه الاستطاعة.
قال الحنفية (١): الاستطاعة أنواع ثلاثة: بدنية ومالية وأمنية، أما الاستطاعة البدنية: فهي صحة البدن، فلا حج على المريض والزَّمِن والمُقْعَد والمفلوج والأعمى وإن وجد قائداً، والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه، والمحبوس، والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف: وهي سلامة الأسباب ووسائل الوصول. ومن جملة الأسباب: سلامة البدن عن الآفات المانعة من القيام بما لا بد منه في سفر الحج، فسر ابن عباس {من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران:٩٧/ ٣] أن السبيل أن يصح بدن العبد، ويكون له ثمن زاد وراحلة، من غير أن يحجب.
وأما الاستطاعة المالية: فهي ملك الزاد والراحلة، بأن يقدر على الزاد ذهاباً وإياباً، وعلى الراحلة ـ وسيلة الركوب، زائداً ذلك عن حاجة مسكنه وما لا بد منه كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذلك؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وزائداً أيضاً عن نفقة عياله الذين تلزمه نفقاتهم إلى حين عودته.
ويشترط في القدرة على الراحلة شروط:
أـ أن تكون مختصة به، فلا يكفي القدرة على راحلة مشتركة يركبها مع غيره على التعاقب. والقدرة اليوم بالاشتراك في السيارات أو البواخر أو الطائرات.
ب ـ أن تكون بحسب أحوال الناس: فمن لا يستطيع الركوب على القتَب (وهو الرَّحْل أو الإكاف الصغير حول سنام البعير) ولم يجد شيئاً آخر كالهودج أو المحمل، لايجب عليه الحج.
جـ ـ أن تطلب بالنسبة للآفاقي: وهو من كان بعيداً عن مكة بثلاثة أيام فأكثر. أما المكي أو القريب من مكة (وهو من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام)، فيجب عليه الحج متى قدر على المشي.
وأما الاستطاعة الأمنية: فهي أن يكون الطريق آمناً بغلبة السلامة ولو بالرشوة؛ لأن استطاعة الحج لا تثبت بدونه، وهو شرط وجوب، في المروي عن أبي حنيفة. وقال بعضهم: إنه شرط أداء.
وأمن المرأة: أن يكون معها أيضاً مَحْرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير فاسق، برحم أو صِهْريّة، أو زوج، يحج بها على نفقتها، ويكره تحريماً أن تحج المرأة بغير المحرم أو الزوج، إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر: وهي مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً، فلو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة، والأصح أنه لا يجب عليها التزوج عند فقد المحرم، ووجود المحرم شرط وجوب، وقيل: شرط أداء. لكن لاتسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا لغلبة الفساد، لكراهة الخلوة بها كالصهرة (الحماية) الشابة.
والذي اختاره الكمال بن الهمام في الفتح أن وجود المحرم مع توافر الصحة وأمن الطريق شروط وجوب الأداء، فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف الطريق، أو لم يوجد زوج ولا محرم.
ثم إن شرط وجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده، فإن جاء وقت الخروج والمال في يده، فليس له أن يصرفه في غيره.
وقال المالكية (١): الاستطاعة: هي إمكان الوصول إلى مكة بحسب العادة، إما ماشياً أو راكباً، أي الاستطاعة ذهاباً فقط، ولا تعتبر الاستطاعة في الإياب إلا إذا لم يمكنه الإقامة بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه، ولا يلزم رجوعه لخصوص بلده.
وتكون الاستطاعة بثلاثة أشياء، وهي:
أـ قوة البدن: أي إمكان الوصول لمكة إمكاناً عادياً بمشي أو ركوب، ببرّ أو بحر، بلا مشقة فادحة، أي عظيمة خارجة عن العادة، أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. والاستطاعة بالقدرة على المشي مما تفرد به المالكية. حتى إن الأعمى القادر على المشي يجب عليه الحج إذا وجد قائداً يقوده. ويكره للمرأة الحج بمشي بعيد.
Fiqih Islam wa Adillatuhu – Wahbah Az-Zuhaili, Juz 3, Hal. 2082-2090
4. Kemampuan Fisik, Finansial, dan Keamanan yang Mewajibkan Haji
Kemampuan yang dimaksud adalah kesanggupan untuk mencapai Mekah, sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. Ali Imran: 97)
Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dan bentuk kemampuan ini.
Pendapat Mazhab Hanafi
Menurut mazhab Hanafi, kemampuan terbagi menjadi tiga jenis: kemampuan fisik, finansial, dan keamanan.
Kemampuan Fisik
Seseorang dikatakan memiliki kemampuan fisik jika memiliki tubuh yang sehat.
Tidak wajib haji bagi orang yang sakit, lumpuh, cacat, atau orang tua renta yang tidak bisa bertahan di atas kendaraan.
Orang buta yang memiliki pemandu juga tidak diwajibkan haji.
Orang yang dipenjara atau dicegah oleh penguasa zalim juga tidak wajib haji.
Ibn Abbas menafsirkan ayat “bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana” bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang sehat tubuhnya, memiliki biaya perjalanan, serta tidak ada halangan yang mencegahnya.
Kemampuan Finansial
Seseorang dikatakan mampu secara finansial jika memiliki bekal dan kendaraan untuk pergi dan pulang dari haji.
Bekal dan kendaraan tersebut harus melebihi kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, pakaian, perabotan rumah tangga, dan biaya nafkah keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan.
Syarat kemampuan memiliki kendaraan:
a. Kendaraan tersebut harus khusus untuk dirinya, tidak boleh kendaraan bersama yang digunakan secara bergantian. Pada zaman sekarang, kemampuan ini diperhitungkan dengan ketersediaan kendaraan umum seperti mobil, kapal, atau pesawat.
b. Kendaraan tersebut harus sesuai dengan kondisi fisik orang tersebut. Jika seseorang tidak mampu naik kendaraan sederhana seperti pelana unta, tetapi tidak memiliki alternatif seperti tandu atau kereta, maka ia tidak wajib haji.
c. Kemampuan memiliki kendaraan ini hanya berlaku bagi orang yang tinggal jauh dari Mekah (tiga hari perjalanan atau lebih). Orang yang tinggal dekat Mekah (kurang dari tiga hari perjalanan) wajib haji jika mampu berjalan kaki.
Kemampuan dalam Keamanan
Jalur perjalanan harus aman dengan dominasi keselamatan, bahkan jika harus membayar suap agar bisa melewati jalan yang aman.
Dalam mazhab Hanafi, keamanan ini dianggap sebagai syarat wajib haji, menurut riwayat dari Abu Hanifah. Namun, menurut sebagian ulama lain, ini adalah syarat sahnya pelaksanaan haji.
Keamanan bagi perempuan:
Wanita harus ditemani mahram baligh, berakal, amanah, dan bukan fasik dari kalangan keluarga atau suami yang ikut berhaji bersamanya dengan biaya wanita tersebut.
Jika perjalanan haji memakan waktu tiga hari atau lebih, maka haram bagi wanita bepergian tanpa mahram atau suami. Jika tetap berangkat tanpa mahram, hajinya tetap sah tetapi makruh.
Wanita tidak wajib menikah demi mendapatkan mahram untuk berhaji.
Dalam pandangan sebagian ulama, keberadaan mahram adalah syarat wajib haji, sementara menurut pendapat lain, ini adalah syarat sahnya pelaksanaan haji.
Di zaman sekarang, wanita tidak dianjurkan bepergian hanya dengan saudara sepersusuan karena dikhawatirkan terjadinya fitnah, begitu juga dengan mertua muda (suami dari saudari iparnya).
Pendapat Al-Kamal bin Al-Humam dalam Fathul Qadir: Syarat mahram, kesehatan tubuh, dan keamanan perjalanan adalah syarat sahnya pelaksanaan haji. Jika seseorang terhalang oleh sakit, ketakutan di perjalanan, atau tidak memiliki mahram/suami, maka ia wajib berwasiat agar dihajikan jika memungkinkan.
Syarat finansial (bekal dan kendaraan) harus terpenuhi saat waktu keberangkatan dari negaranya. Jika sudah ada dana ketika waktu berangkat tiba, maka tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.
Pendapat Mazhab Maliki
Mazhab Maliki mendefinisikan kemampuan sebagai kesanggupan mencapai Mekah sesuai kebiasaan, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara.
Kemampuan hanya diperhitungkan untuk perjalanan pergi. Tidak wajib memiliki biaya pulang kecuali jika ia tidak bisa menetap di Mekah atau di daerah lain yang layak ditinggali.
Kemampuan ini terbagi menjadi tiga aspek:
Kemampuan Fisik
Seseorang harus mampu mencapai Mekah dengan cara yang wajar, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara, baik melalui jalur darat atau laut.
Jika perjalanannya menyebabkan kesulitan luar biasa yang melampaui kebiasaan, maka ia tidak diwajibkan haji. Namun, kesulitan biasa tetap harus diterima karena safar adalah bagian dari kesulitan.
Mazhab Maliki memiliki keunikan dalam hal ini: jika seseorang bisa berjalan kaki ke Mekah, maka ia wajib haji meskipun tidak memiliki kendaraan.
Bahkan, seorang tunanetra yang mampu berjalan dengan bimbingan seorang pemandu tetap wajib berhaji.
Wanita tidak dianjurkan berhaji dengan berjalan kaki jika perjalanannya jauh, karena dikhawatirkan akan mengalami kesulitan.
ب ـ ووجود الزاد المبلِّغ بحسب أحوال الناس وبحسب عوائدهم، ويقوم مقام الزاد الصنعة إذا كانت لا تزري بصاحبها وتكفي حاجته.
ويدل ذلك على أن المالكية لم يشترطوا وجود الزاد والراحلة بالذات، فالمشي يغني عن الراحلة لمن قدر عليه، والصنعة التي تدر ربحاً كافياً تغني عن اصطحاب الزاد أو النفقة عليه.
وتتحقق الاستطاعة بالقدرة على الوصول إلى مكة، ولو بثمن شيء يباع على المفلس من ماشية وعقار وكتب علم وآلة صانع ونحوها، أو حتى ولو صار فقيراً بعد حجه، أو ولو ترك أولاده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس إن لم يخش عليهم هلاكاً أو أذىً شديداً، بأن كان الشأن عدم الصدقة عليهم أو عدم من يحفظهم.
ولا يجب الحج بالاستدانة ولو من ولده إذا لم يرج وفاء، وبالعطية من هبة أو صدقة بغير سؤال، ولا بالسؤال مطلقاً أي سواء أكانت عادته السؤال أم لا، لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر، وعلم أو ظن الإعطاء في السفر ما يكفيه، يجب عليه الحج، أي أن معتاد السؤال في بلده يجب عليه الحج بشرط ظن الإعطاء، وإلا فلا يجب عليه.
جـ ـ توافر السبيل: وهي الطريق المسلوكة بالبر أو بالبحر متى كانت السلامة فيه غالبة، فإن لم تغلب فلا يجب الحج إذا تعين البحر طريقاً. ويكره للمرأة الحج في ركوب بحر إلا أن تختص بمكان في السفينة.
وهذا يتطلب كون الطريق آمناً على النفس والمال من غاصب وسارق وقاطع طريق: إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه، فقد يكون الدينار ذا بال بالنسبة لشخص، ولا شأن له بالنسبة لآخر.
ويزاد في حق المرأة: أن يكون معها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو صهرية (١) من محارمها، أو رفقة مأمونة عند عدم الزوج أو المحرم في حج الفرض ومنه النذر والحنث، سواء أكانت الرفقة نساء فقط، أم مجموعاً من الرجال والنساء. وإذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة، فلو فعلت صح حجها مع الإثم.
وقال الشافعية (٢): للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (٨٩ كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة:
الأول ـ القدرة البدنية: بأن يكون صحيح الجسد، قادراً أن يثبت على الراحلة بلا ضرر شديد أو مشقة شديدة، وإلا فهو ليس بمستطع بنفسه. وعلى الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائداً يقوده ويهديه عند نزوله، ويركبه عند ركوبه. والمحجور عليه بسفه يجب عليه الحج كغيره، لكن لا يدفع المال إليه لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو يرسل معه شخصاً ثقة ينوب عن الولي، ولو بأجرة مثله، إن لم يجد متبرعاً كافياً، لينفق عليه بالمعروف.
الثاني ـ القدرة المالية: بوجود الزاد وأوعيته، ومؤنة (كلفة) ذهابه لمكة وإيابه (أي رجوعه منها إلى بلده، وإن لم يكن له فيها أهل وعشيرة).
فإن كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده، وسفره طويل (مرحلتان فأكثر أي ٩٨ كم)، لم يكلف الحج، حتى ولو كسب في يوم كفاية أيام؛ لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وإذا قدر عدم الانقطاع، فالجمع بين تعب السفر والكسب، فيه مشقة عظيمة. وذلك خلافاً لمذهب المالكية السابق في الاكتفاء بالصنعة أثناء السفر. أما إن كان السفر قصيراً، كأن كان بمكة، أو على دون مرحلتين منها، وهو يكتسب في يوم كفايةأيام، كُلِّف الحج، لقلة المشقة حينئذ.
الثالث ـ وجود الراحلة (وسيلة الركوب) الصالحة لمثله بشراء بثمن المثل، أو استئجار بأجرة المثل، لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا، خلافاً للمالكية، ولكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجاً من خلاف من أوجبه. وهذا الشرط من القدرة المالية أيضاً.
ومن كان بينه ومن مكة دون مرحلتين، وهو قوي على المشي، يلزمه الحج، فإن ضعف عن المشي، بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر، فهو كالبعيد، فيشترط في حقه وجود الراحلة.
Pendapat Mazhab Maliki (Lanjutan)
B. Kemampuan Finansial
Kemampuan finansial ditentukan oleh ketersediaan bekal yang cukup untuk mencapai Mekah sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat.
Keahlian atau keterampilan yang bisa menghasilkan pendapatan selama perjalanan dapat menggantikan kebutuhan membawa bekal atau nafkah.
Mazhab Maliki tidak mensyaratkan keberadaan bekal dan kendaraan secara khusus. Jika seseorang mampu berjalan kaki, maka kendaraan tidak menjadi syarat wajib haji. Begitu pula jika ia memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah selama perjalanan.
Seseorang tetap dianggap mampu berhaji jika ia bisa mencapai Mekah meskipun dengan menjual harta seperti hewan ternak, tanah, buku keilmuan, atau peralatan kerja.
Haji tetap wajib meskipun setelahnya ia menjadi miskin atau meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang mengharuskan mereka menerima sedekah, asalkan mereka tidak sampai terlantar atau mengalami kesulitan berat.
Tidak wajib haji jika harus berutang, baik kepada anaknya sendiri maupun orang lain, kecuali jika ada harapan kuat untuk bisa melunasinya.
Tidak wajib berhaji dengan menerima hibah atau sedekah kecuali jika pemberian tersebut diberikan tanpa ia meminta.
Tidak wajib berhaji dengan mengemis, kecuali jika seseorang memang terbiasa mengemis di daerahnya dan yakin atau menduga kuat bahwa selama perjalanan ia akan mendapatkan sedekah yang cukup untuk menutupi kebutuhan hajinya.
C. Keamanan Perjalanan
Jalan yang ditempuh harus umumnya aman, baik melalui darat maupun laut. Jika satu-satunya jalur perjalanan adalah laut dan keamanannya tidak terjamin, maka tidak wajib berhaji.
Wanita dilarang bepergian sendirian menggunakan kapal laut, kecuali jika ada ruangan khusus yang terjaga dalam kapal.
Keamanan ini mencakup keselamatan jiwa dan harta dari perampokan, pencurian, atau ancaman lainnya. Jika seseorang memiliki sedikit harta tetapi cukup berarti bagi dirinya, maka ancaman kehilangan tetap menjadi pertimbangan dalam kewajiban haji.
Bagi wanita, selain faktor keamanan umum, harus ada suami atau mahram (baik hubungan darah, sepersusuan, atau pernikahan) yang menemaninya dalam perjalanan haji.
Jika tidak ada suami atau mahram, maka dalam haji fardu (termasuk haji karena nadzar atau kafarat), wanita boleh berangkat dengan rombongan terpercaya, baik yang terdiri dari wanita saja maupun gabungan pria dan wanita yang amanah.
Wanita yang masih dalam masa iddah karena talak atau wafat suami tidak boleh berhaji sebelum masa iddahnya selesai. Jika tetap berangkat, hajinya tetap sah tetapi berdosa.
Pendapat Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i menetapkan tujuh syarat kemampuan untuk seseorang yang ingin berhaji atau berumrah sendiri jika jaraknya lebih dari dua marhalah (±89 km) dari Mekah. Ketujuh syarat ini mencakup tiga jenis kemampuan yang telah disebutkan sebelumnya (fisik, finansial, dan keamanan).
Kemampuan Fisik
Harus sehat dan mampu bertahan di atas kendaraan tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan.
Orang buta wajib berhaji jika memiliki pemandu yang dapat menuntunnya saat berjalan, membantunya naik kendaraan, dan membimbingnya selama perjalanan.
Orang yang mengalami gangguan akal (safih/mubazir) tetap wajib haji, tetapi hartanya tidak boleh diberikan langsung kepadanya karena dikhawatirkan akan dihamburkan.
Dalam kasus ini, walinya boleh:
Menemani langsung untuk mengurus kebutuhannya selama perjalanan.
Mengutus seseorang yang dapat dipercaya untuk mengurusnya, dengan biaya dari hartanya sendiri atau biaya sewa yang wajar jika tidak ada orang yang bersedia secara sukarela.
Kemampuan Finansial
Harus memiliki bekal dan biaya perjalanan yang cukup untuk pergi dan kembali ke tanah airnya.
Jika seseorang mampu mencari nafkah harian tetapi perjalanannya jauh (lebih dari dua marhalah / 98 km), ia tidak wajib haji. Sebab, kemungkinan ia tidak bisa mencari nafkah selama perjalanan dan perjalanan jauh dapat menyebabkan kesulitan besar.
Namun, jika perjalanan kurang dari dua marhalah, misalnya seseorang tinggal di Mekah atau dekat dengannya, dan ia mampu mencari nafkah harian yang mencukupi kebutuhannya, maka ia tetap wajib haji karena beban perjalanannya lebih ringan.
Keberadaan Kendaraan (Transportasi)
Jika jaraknya dua marhalah atau lebih dari Mekah, maka wajib memiliki kendaraan yang layak untuk dirinya, baik dengan membelinya maupun menyewanya dengan harga wajar.
Kemampuan berjalan kaki tidak menggugurkan kewajiban memiliki kendaraan bagi orang yang tinggal jauh dari Mekah, berbeda dengan pandangan Mazhab Maliki. Namun, disunnahkan untuk berjalan kaki bagi yang mampu, guna keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkannya.
Jika jaraknya kurang dari dua marhalah dan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib berhaji dengan berjalan kaki. Jika tidak mampu berjalan kaki karena sakit atau kelemahan, maka ia sama seperti orang jauh yang membutuhkan kendaraan.
ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه الحال أو المؤجل، لآدمي أم لله تعالى كنذر وكفارة، وعن مؤنة (١) أي نفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه، لئلا يضيعوا، وقد قال صلّى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» (٢).
والأصح كون الزاد والراحلة فاضلين أيضاً عن مسكنه اللائق به وعن خادمه المحتاج إليه لمنصب أو عجز، لاحتياجه لهما في الحال.
والأصح أنه يلزم المرء صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وتوابعهما. ويلزم من له مستغلات (أماكن أو دور للاستثمار) يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها لما ذكرفي الأصح، كما يلزمه صرفها لوفاء دينه.
الرابع ـ وجود الماء والزاد وعلف الدابة في المواضع المعتاد حمله منها، بثمن المثل: وهو القدر المناسب به في ذلك الزمان والمكان، وإن غلت الأسعار. فإن لم يوجدوا، أو وجد أحدهم، أو وجد بأكثر من ثمن المثل، لم يلزمه النسك (الحج والعمرة). وهذا شرط أيضاً في القدرة المالية.
الخامس ـ الاستطاعة الأمنية: أمن الطريق ولو ظناً على نفسه وماله في كل مكان بحسب ما يليق به، والمراد هو الأمن العام، فلو خاف على نفسه أو زوجه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رَصديّاً (وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئاً)، ولا طريق له سواه، لم يجب الحج عليه، لحصول الضر.
وإذا تحقق الأمن بالخفارة أو الحراسة في غالب الظن، وجب استئجار الحارس على الأصح، إن كان قادراً على أجر المثل.
السادس ـ أن يكون مع المرأة زوج، أو مَحْرم بنسب أو غيره، أو نسوة ثقات؛ لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة أو مع جماعة، لخوف استمالتها وخديعتها، ولخبر الصحيحين: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» ولا يشترط كون الزوجة والمحرم ثقة؛ لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي.
وأما النسوة فيشترط فيهن الثقة لعدم الأمن، والبلوغ، لخطر السفر، ويكتفى بالمراهقات في رأي المتأخرين، وأن يكنَّ ثلاثاً غير المرأة؛ لأنه أقل الجمع، ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة. وهذا كله شرط للوجوب. أما الجواز فيجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام (الفرض) مع المرأة الثقة على الصحيح. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، والأصح أنه يلزم المرأة أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.
أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب، فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة، بل ولا مع النسوة الخلص، لكن لو تطوعت بحج، ومعها محرم، فمات، فلها إتمامه، ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها.
السابع ـ إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه. وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو شوال إلى عشر ذي الحجة، فلا يجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت.
وقال الحنابلة (١): الاستطاعة المشترطة: هي القدرة على الزاد والراحلة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره: «سئل النبي صلّى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» (٢) روى ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مايوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» (٣).
واتفق الشافعية في الأصح والحنابلة على أنه لا يلزم الحج إذا بذل المال ولد أو أجنبي، ولا يجب قبوله، لما في قبول المال من المنة.
ورأى الحنابلة كالشافعية أن من تكلف الحج ممن لا يلزمه، وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة ونحوها، ولايسأل الناس، استحب له الحج، لقوله تعالى: {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} [الحج:٢٧/ ٢٢] فقدم الرجال أي المشاة، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وخروجاً من الخلاف. ويكره الحج لمن حرفته السؤال.
والزاد المشروطة عند الحنابلة كالشافعية: وهو ما يحتاج إليه في ذهابه
ورجوعه، من مأكول ومشروب وكسوة، ويلزمه شراؤه بثمن المثل، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله.
ويلزمه حمل الزاد والماء وعلف البهائم إن لم يجده في طريقه، فإن وجده في المنازل المعتادة، لم يلزمه حمله؛ لأن هذا يشق عليه ولم تجر العادة به.
Pendapat Mazhab Syafi’i (Lanjutan)
Ketersediaan Air, Bekal, dan Pakan Hewan
Bekal perjalanan harus melebihi kebutuhan dasar dan tidak mengganggu kewajiban lain seperti melunasi utang yang telah jatuh tempo (baik kepada manusia maupun kepada Allah, seperti nazar dan kafarat).
Bekal juga harus melebihi nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya selama ia pergi haji, agar mereka tidak terlantar. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”
Harta yang tidak wajib dijual untuk biaya haji:
Rumah tinggal yang layak bagi dirinya.
Pembantu yang dibutuhkan karena jabatan atau kelemahan fisik.
Harta yang wajib dijual untuk biaya haji:
Modal usaha (uang dagangan).
Properti investasi (seperti rumah atau tempat usaha yang tidak digunakan untuk keperluan dasar).
Jika seseorang tidak menemukan air, bekal, atau pakan hewan di tempat yang biasa tersedia dengan harga normal, atau hanya bisa didapatkan dengan harga yang sangat tinggi, maka ia tidak wajib berhaji.
Keamanan Perjalanan
Jalur perjalanan harus aman, baik bagi diri sendiri maupun harta bendanya.
Jika ada ancaman serius seperti binatang buas, perampok, atau penyergapan, dan tidak ada jalan lain yang lebih aman, maka kewajiban haji gugur.
Jika keamanan bisa diperoleh dengan menyewa pengawal dan ia mampu membayarnya dengan harga wajar, maka wajib baginya untuk menyewa pengawal tersebut.
Persyaratan Tambahan bagi Wanita
Wanita tidak boleh bepergian sendirian. Ia harus disertai oleh Suami, atau mahram dari hubungan darah, persusuan, atau pernikahan, atau rombongan wanita terpercaya, terutama dalam haji wajib.
Hadis Rasulullah ﷺ:
“Seorang wanita tidak boleh bepergian selama dua hari kecuali bersama suaminya atau mahramnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Suami atau mahram tidak disyaratkan harus orang yang sangat terpercaya, karena ikatan darah atau pernikahan sudah cukup sebagai penghalang.
Jika seorang wanita hanya memiliki satu teman wanita untuk menemaninya, itu tidak cukup. Minimal harus ada tiga wanita di luar dirinya.
Dalam haji fardu, wanita boleh berangkat dengan seorang wanita lain yang terpercaya, meskipun tanpa mahram.
Dalam haji sunnah atau perjalanan lain yang tidak wajib, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, bahkan meskipun dengan rombongan wanita terpercaya.
Jika seorang wanita sedang dalam perjalanan haji sunnah bersama mahramnya, kemudian mahramnya meninggal dunia di tengah perjalanan, ia boleh melanjutkan hajinya sendirian.
Seorang wanita boleh berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam meskipun sendirian.
Jika seorang wanita tidak menemukan mahram yang bersedia menemani kecuali dengan bayaran, maka ia wajib membayar mahram tersebut.
Waktu yang Cukup untuk Berangkat
Jika seseorang hanya memperoleh kemampuan (fisik, finansial, atau keamanan) setelah waktu haji hampir habis sehingga tidak cukup untuk menunaikannya, maka haji tidak wajib bagi dirinya pada tahun itu.
Kewajiban haji dilihat ketika awal musim haji (bulan Syawal hingga 10 Dzulhijjah). Jika seseorang tidak mampu di rentang waktu ini, maka ia tidak terkena kewajiban haji.
Pendapat Mazhab Hanbali
Definisi Kemampuan dalam Haji
Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kemampuan finansial dalam haji hanya mencakup:
- Bekal yang cukup.
- Kendaraan yang layak untuk perjalanan.
Hal ini didasarkan pada hadis:
“Rasulullah ﷺ ditanya: ‘Apa yang dimaksud dengan sabīl (jalan) dalam haji?’ Beliau menjawab: ‘Bekal dan kendaraan’.” (HR. Tirmidzi)
Dalam riwayat lain, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ:
“Wahai Rasulullah, apa yang mewajibkan haji?” Beliau menjawab: “Bekal dan kendaraan.”
Tidak Wajib Menerima Hibah atau Pemberian Orang Lain
Jika seorang anak atau orang lain menawarkan biaya haji kepada seseorang, ia tidak wajib menerimanya, karena menerima pemberian bisa dianggap sebagai beban moral. Pandangan ini juga dianut oleh Mazhab Syafi’i.
Haji dengan Berjalan Kaki atau Mencari Nafkah di Perjalanan
Jika seseorang tidak memiliki harta tetapi mampu berjalan kaki atau bekerja selama perjalanan tanpa meminta-minta, maka disunnahkan baginya untuk berhaji.
Allah berfirman:
“Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus.” (QS. Al-Hajj: 27)
Berjalan kaki menunjukkan kesungguhan dalam ibadah dan keluar dari perbedaan pendapat tentang wajibnya berjalan kaki bagi yang mampu.
Namun, dilarang bagi orang yang kebiasaannya mengemis untuk berhaji dengan cara meminta-minta.
Persyaratan Bekal dalam Pandangan Hanbali
Bekal yang wajib dipersiapkan adalah yang mencakup kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian selama perjalanan pergi dan pulang.
Jika tidak ada bekal di sepanjang perjalanan, maka wajib membawanya dari awal.
Jika bekal tersedia di rute perjalanan, maka tidak wajib membawanya dari awal, karena ini akan menjadi beban berat yang tidak lazim dilakukan.
ويشترط أيضاً القدرة على وعاء الزاد والماء؛ لأنه لا بد منه.
ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه؛ لأنه لا بد منه، فإن لم يحتج إليه لم يعتبر.
وأما الراحلة أو المركوب: فيشترط أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه، وأن يجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله. ويطلب وجود الراحلة مع بعد المسافة فقط عن مكة، ولو قدر على المشي، لأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبعد المسافة: ما تقصر فيه الصلاة، أي مسيرة يومين معتدلين، ولا تعتبر الراحلة فيما دون مسافة القصر، من مكي وغيره بينه وبين مكة دون المسافة، ويلزمه المشي للقدرة على المشي فيها غالباً، ولأن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها المشي للقدرة على المشي فيها غالباً، ولا يخشى فيها عطب إذا حدث انقطاع بها، إلا مع عجز لكبر ونحوه كمرض، فتعتبر الراحلة، حتى فيما دون المسافة للحاجة إليها إذن. ولا يلزمه السير حبواً وإن أمكنه لمزيد مشقته.
ويشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه، دون ما بعد رجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد، وقد قال صلّى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» (١).
Syarat Kemampuan dalam Haji
Memiliki Wadah untuk Bekal dan Air
Seseorang harus memiliki tempat atau wadah untuk menyimpan bekal makanan dan air karena ini merupakan kebutuhan utama dalam perjalanan.
Kebutuhan bekal ini dipertimbangkan baik untuk jarak dekat maupun jauh jika memang diperlukan. Namun, jika seseorang tidak memerlukan bekal, maka syarat ini tidak diberlakukan baginya.
Memiliki Kendaraan yang Layak
Kendaraan atau tunggangan yang digunakan harus layak dan sesuai dengan kondisinya, baik dengan cara membeli atau menyewanya untuk perjalanan pergi dan pulang.
Ia juga harus memiliki segala perlengkapan yang diperlukan untuk kendaraan tersebut agar dapat digunakan dengan baik.
Kewajiban Memiliki Kendaraan Berdasarkan Jarak Perjalanan
Jika jarak perjalanan jauh (≥ 2 hari perjalanan normal atau sekitar 80-90 km): Seseorang wajib memiliki kendaraan meskipun ia mampu berjalan kaki.
Ini karena dalam hadis, “kemampuan (istitha’ah) dalam haji adalah memiliki bekal dan kendaraan.”
Jika jarak perjalanan dekat (< 2 hari perjalanan):
Tidak disyaratkan memiliki kendaraan, baik bagi penduduk Makkah maupun yang tinggal dalam jarak tersebut.
Ia wajib berjalan kaki jika mampu, karena biasanya orang masih kuat berjalan dalam jarak tersebut dan tingkat kesulitannya ringan.
Namun, jika ia mengalami kelemahan fisik (seperti usia tua atau sakit), maka kendaraan tetap menjadi syarat, meskipun jaraknya dekat.
Ia tidak wajib merangkak (berjalan dengan tangan dan lutut), meskipun secara teori memungkinkan, karena hal itu terlalu sulit.
Bekal dan Kendaraan Harus Berlebih dari Kebutuhan Keluarga
Bekal dan kendaraan yang dimiliki harus melebihi kebutuhan nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya selama masa keberangkatan hingga kepulangan.
Tidak disyaratkan lebih dari kebutuhan setelah ia pulang, karena yang menjadi prioritas adalah memastikan keluarganya tidak terlantar selama kepergiannya.
Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah ﷺ:
“Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”
Dengan demikian, seseorang tidak wajib berhaji jika:
- Ia tidak memiliki kendaraan dalam jarak jauh.
- Ia tidak memiliki wadah untuk membawa bekal dan air.
Bekal dan kendaraan yang dimilikinya masih dibutuhkan oleh keluarganya untuk kehidupan dasar mereka selama ia pergi haji.
كتاب الأم للشافعى ج٧ص٧١
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَمَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ أَنْ يَمْشِيَ إنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكِبَ وَأَهْرَاقَ دَمًا احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا نَذَرَ كَمَا نَذَرَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَمٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُطِقْ شَيْئًا سَقَطَ عَنْهُ كَمَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا وَلَا يُطِيقُ الْقُعُودَ فَيُصَلِّي مُضْطَجِعًا وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ وَالصَّلَاةِ أَنَّ النَّاسَ أَصْلَحُوا أَمْرَ الْحَجِّ بِالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّسُكِ وَلَمْ يُصْلِحُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ إلَّا بِالصَّلَاةِ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَلَا يَمْشِي أَحَدٌ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إلَّا حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (قَالَ الرَّبِيعُ) وَلِلشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَوْلٌ آخَرُ إنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَحَنِثَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ تَجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْيَمِينَ (قَالَ الرَّبِيعُ) وَسَمِعْت الشَّافِعِيَّ أَفْتَى بِذَلِكَ رَجُلًا فَقَالَ هَذَا قَوْلُك يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ هَذَا هُوَ قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي قَالَ وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا مَعْقُولُ مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ إنَّ كُلَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ النُّسُكِ صَوْمٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إذَا حَنِثَ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا صَوْمٌ وَمَذْهَبُهُ أَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ لِلَّهِ لَا تَكُونُ إلَّا بِفَرْضٍ يُؤَدِّيهِ مِنْ فَرْضِ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَوْ تَبَرُّرًا يُرِيدُ اللَّهَ بِهِ.
فَأَمَّا عَلَى غَلْقِ الْأَيْمَانِ فَلَا يَكُونُ تَبَرُّرًا وَإِنَّمَا يَعْمَلُ التَّبَرُّرَ لِغَيْرِ الْغَلْقِ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا.
(قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَالتَّبَرُّرُ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ شَفَى اللَّهُ فُلَانًا، أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ قَضَى عَنِّي دَيْنًا، أَوْ كَانَ كَذَا أَنْ أَحُجَّ لَهُ نَذْرًا فَهُوَ التَّبَرُّرُ، فَأَمَّا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَقْضِك حَقَّك فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَهَذَا مِنْ مَعَانِي الْأَيْمَانِ لَا مِنْ مَعَانِي النُّذُورِ وَأَصْلُ مَعْقُولِ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي مَعَانِي النُّذُورِ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ فَهَذَا يُوَافِقُ السُّنَّةَ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ شَفَانِي، أَوْ شَفَى فُلَانًا أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، أَوْ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا مِنْ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَمَنْ قَالَ هَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَفِي السَّائِبَةِ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّذْرَ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةً.
وَكَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَفِيَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ
Barangsiapa yang Bernazar untuk Berjalan ke Baitullah
(Imam asy-Syafi’i – rahimahullah – berkata): “Barangsiapa yang bernazar sebagai bentuk ibadah (tabarrur) untuk berjalan menuju Baitullah al-Haram, maka wajib baginya berjalan jika mampu. Jika ia tidak mampu berjalan, maka ia harus berkendara dan menyembelih hewan sebagai bentuk kehati-hatian, karena ia tidak dapat memenuhi nazarnya sebagaimana yang ia janjikan. Namun, secara qiyas, sebenarnya ia tidak wajib menyembelih hewan, karena jika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu, maka kewajiban itu gugur darinya. Seperti orang yang tidak mampu berdiri dalam shalat, maka ia shalat dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk, ia shalat dengan berbaring.
Kami membedakan antara haji dan umrah dengan shalat karena manusia telah menetapkan solusi dalam ibadah haji dengan puasa, sedekah, dan penyembelihan, sementara dalam shalat, mereka tidak menetapkan solusi kecuali dengan shalat itu sendiri.”
(Imam asy-Syafi’i – rahimahullah – berkata): “Tidak ada seorang pun yang berjalan menuju Baitullah kecuali untuk haji atau umrah yang memang diwajibkan baginya.”
(Ar-Rabi’ berkata): “Dan Imam asy-Syafi’i – rahimahullah – memiliki pendapat lain bahwa jika seseorang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah al-Haram lalu melanggar sumpahnya, maka kaffarah sumpah sudah mencukupi baginya, jika niatnya adalah bersumpah.”
(Ar-Rabi’ berkata): “Aku mendengar asy-Syafi’i memberikan fatwa kepada seseorang tentang hal ini, lalu orang itu bertanya, ‘Apakah ini pendapatmu, wahai Abu Abdillah?’ Maka beliau menjawab, ‘Ini adalah pendapat orang yang lebih baik dariku.’ Orang itu bertanya, ‘Siapa dia?’ Beliau menjawab, ‘Atha’ bin Abi Rabah.'”
(Imam asy-Syafi’i – rahimahullah – berkata): “Barangsiapa yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satunya adalah sesuai dengan makna pendapat Atha’, yaitu bahwa setiap orang yang bersumpah untuk melakukan salah satu bentuk ibadah seperti puasa, haji, atau umrah, maka kaffarah sumpah sudah mencukupi baginya jika ia melanggarnya, dan tidak wajib baginya haji, umrah, atau puasa.
Mazhab beliau adalah bahwa amalan kebaikan karena Allah tidak terjadi kecuali dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah atau dalam bentuk ibadah sunah yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
Adapun dalam konteks sumpah yang bersifat ‘ghalaq’ (menekan diri sendiri), maka itu bukan ibadah tabarrur (mendekatkan diri kepada Allah), karena tabarrur dilakukan bukan dalam kondisi keterpaksaan.
Sebagian ulama selain Atha’ berpendapat bahwa orang yang bersumpah untuk berjalan ke Baitullah wajib memenuhinya sebagaimana jika ia bernazar dengan niat tabarrur.”
(Imam asy-Syafi’i – rahimahullah – berkata): “Tabarrur adalah jika seseorang berkata, ‘Demi Allah, jika Allah menyembuhkan si fulan, atau jika si fulan kembali dari safarnya, atau jika utangku terlunasi, maka aku akan berhaji sebagai nazar.’ Inilah tabarrur.
Namun, jika ia berkata, ‘Jika aku tidak melunasi hakmu, maka wajib atasku berjalan ke Baitullah,’ maka ini termasuk makna sumpah, bukan nazar.
Pendapat Atha’ dalam hal ini sejalan dengan makna nazar, yaitu bahwa barangsiapa yang bernazar dalam maksiat kepada Allah, maka ia tidak wajib menunaikannya dan tidak ada kaffarah baginya.
Hal ini sesuai dengan sunnah, sebagaimana seseorang yang berkata, ‘Jika Allah menyembuhkanku atau menyembuhkan si fulan, maka aku akan menyembelih anakku,’ atau ‘Aku akan melakukan sesuatu yang diharamkan,’ maka tidak ada kewajiban apapun baginya.
Demikian pula dalam nazar yang berkaitan dengan bahirah dan saibah, yang telah Allah batalkan karena itu merupakan bentuk maksiat, dan Allah tidak menetapkan kaffarah dalam hal tersebut.”
“Dalam hal ini, terdapat dalil bahwa barangsiapa yang bernazar dalam maksiat kepada Allah, maka ia tidak wajib memenuhinya dan tidak ada kaffarah baginya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sunnah.”
(Ar-Rabi’ berkata): “Imam asy-Syafi’i memberitahukan kepada kami, bahwa Imam Malik meriwayatkan dari Thalhah bin Abdul Malik al-Aili…” WALLAHU A’LAM BISH-SHAWAB.