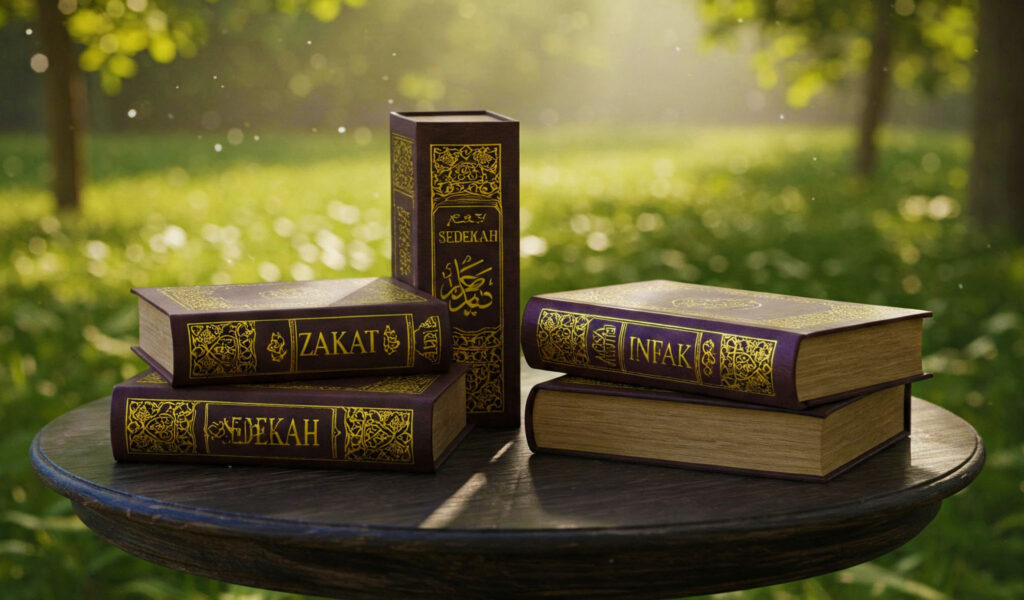Deskripsi masalah
Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai konsep kedermawanan yang berfungsi untuk menyeimbangkan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Tiga konsep utama dalam hal ini adalah zakat, infak, dan sedekah,
Pertanyaan
Adakah perbedaan antara zakat sedekah dan infak ? Mohon penjelasan!
Waalaikum salam
Jawaban
Perbedaan antara Zakat, Sedekah dan Infak dapat dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah dan praktikmya sebagai berikut:
- Zakat “Definisi “: Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan dan peningkatan. Secara istilah, zakat adalah hak wajib yang harus ditunaikan dari harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
Zakat telah diwajibkan sejak di Mekah, namun ketentuan mengenai kadar nisab, jenis harta yang wajib dizakati, serta golongan penerima zakat ditetapkan di Madinah pada tahun kedua hijriah.
Hukum Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat dan shalat, serta merupakan rukun ketiga dalam Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam syariat dengan kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an (8 asnaf dalam QS. At-Taubah: 60).
Jenis zakat meliputi zakat fitrah dan zakat maal (harta) seperti zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan profesi.
Praktik :
Harus memenuhi syarat tertentu, seperti nisab, haul (untuk beberapa jenis), dan kepemilikan penuh.
Tidak boleh diberikan kepada orang tua, anak, atau pasangan karena mereka merupakan tanggungan wajib.
Contoh: Seseorang memiliki usaha dagang dengan keuntungan yang mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan 2,5% dari keuntungannya sebagai zakat maal.
- Sedekah ” Definisi “: Secara etimologis, kata sedekah berasal dari akar kata shidq (kejujuran), sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi:
“Makna penamaan zakat dengan sedekah diambil dari sifat jujur (shidq) dalam kesesuaian antara perbuatan, ucapan, dan keyakinan
Sedekah lebih luas dari zakat dan infak karena tidak terbatas pada harta.
Termasuk segala bentuk kebaikan, seperti senyum, menolong orang lain, atau perbuatan baik lainnya. Dengan kata lain sedekah lebih luas dari zakat walaupun zakat juga bisa disebut sedekah namun tidak semua sedekah disebut zakat karena sedekah beranika ragam.
Praktik :
Tidak ada batasan jumlah atau penerima.
Bisa berupa makanan, pakaian, tenaga, atau hal-hal non-materi.
Contoh: Seseorang membelikan makanan untuk orang miskin atau membantu tetangga tanpa meminta imbalan.
- Infak ” Definisi “: Secara bahasa, infak berarti mengeluarkan sesuatu dari tangan.
Makna infak dalam istilah adalah merujuk pada pengeluaran harta dalam ketaatan kepada Allah, baik yang wajib (seperti infak kepada keluarga ) maupun sunnah (seperti infak fisabilillah).Dengan demikian
Infak lebih luas dibanding zakat dan tidak memiliki ketentuan nisab maupun haul. Bisa diberikan kepada siapa saja, baik kerabat, fakir miskin, ataupun untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, dakwah, dan lainnya.
Infak termasuk nafkah yang wajib, seperti memberi nafkah kepada orang tua, istri, anak, dan keluarga yang menjadi tanggungan.
Praktik :
Bisa bersifat wajib (nafkah kepada keluarga) atau sunnah (memberikan dana ke masjid, lembaga pendidikan, atau kegiatan sosial).
Contoh: Seseorang memberikan sejumlah uang kepada panitia pembangunan masjid atau membantu biaya hidup saudaranya yang kesulitan ekonomi.
Kesimpulan Praktis:
Zakat bersifat wajib, ada ketentuan nisab, haul, dan penerimanya terbatas.
Infak lebih luas, bisa wajib (nafkah keluarga) atau sunnah, dan bisa diberikan ke individu atau fasilitas umum.
Sedekah paling fleksibel, tidak terbatas pada harta, dan mencakup segala bentuk kebaikan.
Jadi, benar bahwa nafkah kepada orang tua tidak boleh menggunakan zakat tetapi wajib diberikan melalui infak. Begitu juga dengan dana untuk prasarana ibadah, gaji guru agama, atau acara keagamaan bisa dibiayai dari infak dan sedekah.
Wallahu a’lam
Referensi:
فقه الزكاة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الجزء الاول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَعْنَى الزَّكَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا
الزَّكَاةُ لُغَةً: مَصْدَرُ زَكَا الشَّيْءُ إِذَا نَمَى وَزَادَ، وَزَكَا فُلَانٌ إِذَا صَلُحَ، فَالزَّكَاةُ هِيَ: الْبَرَكَةُ وَالنَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ وَالصَّلَاحُ (الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ ٣٩٨/١). قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَأَصْلُ الزَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ: الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَالْمَدْحُ، وَكُلُّهُ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ. وَالْأَظْهَرُ – كَمَا قَالَ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ -: أَنَّ أَصْلَ مَادَّةِ “زَكَا” الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ. يُقَالُ زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو زَكَاءً. وَكُلُّ شَيْءٍ ازْدَادَ فَقَدْ زَكَا. وَلَمَّا كَانَ الزَّرْعُ لَا يَنْمُو إِذَا خَلَصَ مِنَ الدَّغَلِ كَانَتْ لَفْظَةُ “الزَّكَاةُ” تَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ أَيْضًا. وَإِذَا وُصِفَ الْأَشْخَاصُ بِالزَّكَاةِ – بِمَعْنَى الصَّلَاحِ – فَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى زِيَادَةِ الْخَيْرِ فِيهِمْ، يُقَالُ: رَجُلٌ زَكِيٌّ، أَيْ زَائِدُ الْحَدِّ مِنْ قَوْمٍ أَزْكِيَاءَ، وَ “زَكَّى الْقَاضِي الشُّهُودَ” إِذَا بَيَّنَ زِيَادَتَهُمْ فِي الْخَبَرِ. وَالزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ تُطْلَقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ. كَمَا تُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحِصَّةِ (قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ: ٥٣٦/١ ط. أُولَى: “الزَّكَاةُ فُعْلَةٌ كَالصَّدَقَةِ، وَهِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، تُطْلَقُ عَلَى عَيْنٍ وَهِيَ الطَّائِفَةُ مِنَ الْمَالِ الْمُزَكَّى بِهَا، وَعَلَى مَعْنَى: وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ التَّزْكِيَةُ زَ. وَمِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا أَتَى مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِالطَّعْنِ عَلَى قَوْلِهِ – عَزَّ وَجَلَّ -: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) ذَاهِبًا إِلَى الْعَيْنِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ، أَعْنِي التَّزْكِيَةَ”). وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْحِصَّةُ الْمُخْرَجَةُ مِنَ الْمَالِ زَكَاةً لِأَنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ الَّذِي أُخْرِجَتْ مِنْهُ، وَتُوَفِّرُهُ فِي الْمَعْنَى، وَتَقِيهِ الْآفَاتِ. كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْوَاحِدِيِّ (الْمَجْمُوعُ: ٣٢٤/٥). وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: نَفْسُ الْمُتَصَدِّقِ تَزْكُو، وَمَالُهُ يَزْكُو: يَطْهُرُ وَيَزِيدُ فِي الْمَعْنَى (مَجْمُوعُ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: ٨/٢٥). وَالنَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ لَيْسَا مَقْصُورَيْنِ عَلَى الْمَالِ، بَلْ يَتَجَاوَزَانِهِ إِلَى نَفْسِ مُعْطِي الزَّكَاةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التَّوْبَةُ: ١٠٣). وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّهَا تُنَمِّي الْفَقِيرَ، وَهِيَ لَفْتَةٌ جَمِيلَةٌ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تُحَقِّقُ نُمُوًّا مَادِّيًا وَنَفْسِيًّا لِلْفَقِيرِ أَيْضًا، بِجَانِبِ تَحْقِيقِهَا لِنَمَاءِ الْغَنِيِّ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
Makna Zakat secara Bahasa dan Syariat
Zakat secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata zakā yang berarti berkembang dan bertambah. Kata zakā fulān digunakan ketika seseorang menjadi baik. Dengan demikian, zakat bermakna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan (Al-Mu‘jam Al-Wasīṭ, 1/398).
Dalam Lisān al-‘Arab disebutkan bahwa asal makna zakat dalam bahasa adalah kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan pujian, dan semua makna ini digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Pendapat yang lebih kuat—sebagaimana dikatakan oleh Al-Wāhidī dan lainnya—bahwa akar kata zakā adalah peningkatan dan pertumbuhan. Dikatakan, “tanaman itu tumbuh” (zakā az-zar‘u yazkū zakā’an). Segala sesuatu yang bertambah disebut zakā. Karena tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik kecuali jika terbebas dari gulma, maka kata zakat juga bermakna kesucian. Jika seseorang digambarkan dengan zakat dalam arti kebaikan, maka maknanya kembali kepada bertambahnya kebaikan dalam dirinya. Dikatakan, “seorang laki-laki itu zaki” (suci dan baik), yakni lebih unggul di antara kaumnya yang bersih (azkiyā’). Istilah zakkā al-qāḍī as-suhūd berarti seorang hakim memverifikasi kejujuran para saksi.
Dalam syariat, zakat merujuk pada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Zakat juga digunakan untuk menyebut tindakan mengeluarkan bagian harta tersebut.
Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Fā’iq (1/536, cet. pertama) menyebutkan bahwa zakat adalah bentuk fu‘lah seperti ṣadaqah. Ia termasuk kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu makna), bisa bermakna suatu benda (harta yang dikeluarkan) maupun suatu tindakan (proses penyucian harta). Dari ketidaktahuan akan hal ini, sebagian orang salah dalam menafsirkan firman Allah: “Dan orang-orang yang berbuat zakat” (Al-Mu’minūn: 4), mereka mengiranya merujuk kepada benda (harta), padahal yang dimaksud adalah tindakan penyucian (tazkiyah).
Bagian harta yang dikeluarkan disebut zakat karena ia menambah keberkahan harta yang tersisa, melindunginya dari musibah, dan membersihkannya secara maknawi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh An-Nawawi yang mengutip dari Al-Wāhidī dalam Al-Majmū‘ (5/324). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa diri orang yang bersedekah menjadi suci, dan hartanya pun menjadi suci dan bertambah dalam makna yang lebih luas (Majmū‘ Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, 8/25). Pertumbuhan dan kesucian yang dihasilkan oleh zakat tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga meliputi diri orang yang menunaikannya. Allah berfirman:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. (At-Taubah: 103)
Al-Azhari menambahkan bahwa zakat juga berfungsi untuk menumbuhkan kesejahteraan fakir miskin, baik secara materi maupun mental. Ini adalah isyarat indah bahwa zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan jiwa dan harta orang kaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِيِّ قَالَ: “اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَفْظَةٌ عَرَبِيَّةٌ مَعْرُوفٌ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، مُسْتَعْمَلَةٌ فِي أَشْعَارِهِمْ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ.” وَقَالَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ: لَا أَصْلَ لِهَذَا الِاسْمِ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ. قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا، فَلَيْسَ الْخِلَافُ فِيهِ مُؤَثِّرًا فِي أَحْكَامِ الزَّكَاةِ. (الْمَجْمُوعُ: ٥/٣٢٤) إِذَا عَرَفْنَا مَا تَقَدَّمَ لَمْ نَجِدْ مَجَالًا لِدَعْوَى الْمُسْتَشْرِقِ الْيَهُودِيِّ الْمَعْرُوفِ “شَاخْت” كَاتِبِ مَادَّةِ “زَكَاة” فِي دَائِرَةِ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُتَرْجَمَةِ، حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اسْتَعْمَلَ كَلِمَةَ “زَكَاة” بِمَعْنًى أَوْسَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا اللُّغَوِيِّ بِكَثِيرٍ، آخِذًا مِنْ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الْيَهُودِ فِي الْيَهُودِيَّةِ – الْآرَامِيَّةِ “زَاكُوت”). قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَهُوَ مَا يَزَالُ فِي مَكَّةَ يَسْتَعْمِلُ كَلِمَةَ “زَكَاة” وَمُشْتَقَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ مَادَّةِ “زَكَا” بِمَعْنَى “ظَهَرَ” تَرْتَبِطُ بِالزَّكَاةِ، بِحَسَبِ الْإِحْسَاسِ اللُّغَوِيِّ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَهَذِهِ الْمُشْتَقَّاتُ نَفْسُهَا لَا يَكَادُ يَكُونُ لَهَا فِي الْقُرْآنِ سِوَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي لَيْسَ عَرَبِيًّا أَصِيلًا، بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ الْيَهُودِيَّةِ: وَهُوَ “التَّقْوَى” (دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ: ١٠/ ٣٥٥، ٣٥٦). وَهَؤُلَاءِ الْمُسْتَشْرِقُونَ مِنْ شَاخْتَ وَأَمْثَالِهِ لَهُمْ غَرَامٌ جُنُونِيٌّ بِنِسْبَةِ كُلِّ مَا يَسْتَطِيعُونَهُ مِنْ مَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِ، وَأَلْفَاظِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَفْكَارِهِ، وَأَخْلَاقِهِ إِلَى مَصَادِرَ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ، أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ مَصَادِرَ شَرْقِيَّةٍ أَوْ غَرْبِيَّةٍ، لَا يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ. وَحَسْبُنَا فِي الرَّدِّ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَمْرَانِ:
Imam An-Nawawi menukil dari penulis kitab Al-Hawi yang berkata: “Ketahuilah bahwa kata ‘zakat’ adalah lafaz dalam bahasa Arab yang sudah dikenal sebelum datangnya syariat, digunakan dalam syair-syair mereka, dan hal itu lebih banyak daripada sekadar membutuhkan dalil.” Sementara itu, Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa kata ini tidak memiliki asal dalam bahasa Arab, melainkan hanya dikenal melalui syariat. Penulis Al-Hawi pun menanggapi: “Pendapat ini, meskipun keliru, namun perbedaan pandangan dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap hukum zakat.” (Al-Majmu’ 5/324)
Jika kita telah memahami penjelasan di atas, maka tidak ada ruang untuk menerima klaim dari orientalis Yahudi terkenal, Schacht, yang menulis entri “Zakat” dalam Encyclopaedia of Islam yang telah diterjemahkan. Ia beranggapan bahwa Nabi Muhammad ﷺ menggunakan kata “zakat” dengan makna yang jauh lebih luas dibandingkan penggunaan bahasa aslinya. Ia menilai bahwa Nabi mengambil makna tersebut dari penggunaan kata ini dalam bahasa Yahudi-Aram, yaitu “Zakut”. Ia juga mengatakan bahwa sejak masih berada di Makkah, Nabi ﷺ telah menggunakan kata “zakat” dan berbagai bentuk turunannya dari akar kata “zaka” dalam makna “muncul” yang terkait dengan zakat, sebagaimana pemahaman bahasa Arab saat itu. Ia juga mengklaim bahwa turunan kata tersebut dalam Al-Qur’an hampir selalu digunakan dalam makna yang bukan asli bahasa Arab, melainkan berasal dari Yahudi, yakni dalam arti “ketakwaan”. (Encyclopaedia of Islam, 10/355-356)
Para orientalis seperti Schacht dan lainnya memiliki obsesi yang tidak rasional dalam mengaitkan setiap konsep dalam Islam—baik istilah, hukum, pemikiran, maupun akhlaknya—kepada sumber-sumber Yahudi, Nasrani, atau sumber Timur dan Barat lainnya. Mereka tidak mengikuti metode ilmiah, melainkan hanya sekadar mengikuti prasangka dan hawa nafsu.
Adapun bantahan terhadap pernyataan tersebut cukup dengan dua hal sebagaimana berikut:
الأَوَّلُ: أَنَّ الْقُرْآنَ اسْتَعْمَلَ الزَّكَاةَ فِي مَعْنَاهَا الْمَعْرُوفِ لَدَى الْمُسْلِمِينَ مُنْذُ أَوَائِلِ الْعَهْدِ الْمَكِّيِّ، كَمَا تَرَى ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ (آيَةُ ١٥٦)، وَسُورَةِ مَرْيَمَ (آيَةُ ٤١، ٥٥)، وَسُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ (آيَةُ ٧٢)، وَسُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ (آيَةُ ٤)، وَسُورَةِ النَّمْلِ (آيَةُ ٣)، وَسُورَةِ الرُّومِ (آيَةُ ٣٩)، وَسُورَةِ لُقْمَانَ (آيَةُ ٣)، وَسُورَةِ فُصِّلَتْ (آيَةُ ٧). وَمَعْرُوفٌ بِيَقِينٍ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْعِبْرِيَّةَ، وَلَا أَيَّ لُغَةٍ غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْيَهُودِ إِلَّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَتَى وَكَيْفَ أَخَذَ عَنِ الْيَهُودِ وَالْيَهُودِيَّةِ كَمَا زَعَمَ “شَاخْتُ”؟.
الثَّانِيُّ: أَنَّ مِنَ الْمُجَازَفَةِ الْمُنَافِيَةِ لِخُلُقِ الْعُلَمَاءِ وَمَنَاهِجِ التَّحْقِيقِ أَنْ يَزْعُمَ زَاعِمٌ نَقْلَ لُغَةٍ عَنْ أُخْرَى إِذَا وُجِدَ كَلِمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي مَعْنَاهَا بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ، فَإِنَّ الِاشْتِرَاكَ لَا يَقْتَضِي ضَرُورَةً نَقْلَ إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ عَنِ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِنْ تَعَيَّنَ إِحْدَاهُمَا بِأَنَّهَا النَّاقِلَةُ وَالْأُخْرَى مَنْقُولَةٌ عَنْهَا – تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ، وَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ، فَمَنِ اتَّخَذَ هَذَا النَّهْجَ لَهُ دَيْدَنًا، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ أَمَانَةِ الْعِلْمِ، وَأَخْلَاقِ الْعُلَمَاءِ.
Pertama: Sesungguhnya Al-Qur’an telah menggunakan kata “zakat” dalam makna yang sudah dikenal oleh kaum Muslimin sejak awal masa Makkah. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-A’raf (ayat 156), Surah Maryam (ayat 41 dan 55), Surah Al-Anbiya’ (ayat 72), Surah Al-Mu’minun (ayat 4), Surah An-Naml (ayat 3), Surah Ar-Rum (ayat 39), Surah Luqman (ayat 3), dan Surah Fussilat (ayat 7). Sudah diketahui dengan yakin bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui bahasa Ibrani atau bahasa selain Arab. Selain itu, beliau tidak pernah berhubungan dengan kaum Yahudi kecuali setelah hijrahnya ke Madinah. Maka, kapan dan bagaimana beliau dapat mengambil istilah dari ajaran Yahudi sebagaimana yang diklaim oleh “Shaqt”?
Kedua: Termasuk tindakan gegabah yang bertentangan dengan etika ilmuwan dan metode penelitian yang benar adalah klaim bahwa suatu bahasa mengambil kata dari bahasa lain hanya karena ada kesamaan makna dalam kedua bahasa tersebut. Sebab, kesamaan dalam suatu kata tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu bahasa mengambilnya dari yang lain. Jika salah satu bahasa harus dianggap sebagai sumber dan yang lain sebagai hasil serapan tanpa bukti yang jelas, maka itu adalah tindakan yang sewenang-wenang dan pengutamaan tanpa dasar. Barang siapa yang menjadikan metode ini sebagai kebiasaannya, maka ia telah menyimpang dari amanah keilmuan dan etika para ulama.
الموسوعة الفقهية الكويتيه ج١ص ٢٣٠-٢٣٣
[١ – معنى الزكاة وحكمها وفضلها]
شرع الله لعباده عبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، والصدقة، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه، كالصيام، ونوع الله العبادات ليختبر العباد، من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها.
المال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون حلالا، وأن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، وأن يؤدي حق الله فيه.
الزكاة: هي النماء والزيادة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص.
فرضت الزكاة في مكة، أما تقدير نصابها، وبيان الأموال التي تزكى، وبيان مصارفها فكان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة.
[حكم الزكاة:]
الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (التوبة/١٠٣).
حكمة مشروعية الزكاة:]
ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال، ليكون سيدا له لا عبدا له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. الزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة الإيمان في قلب صاحبها، وزيادة في خلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه، وهو إرضاء ربه سبحانه، والفوز بجنته. نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال، وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية التملك، وإيجاب الحقوق في المال، وتحديدها وتقديرها، وبيان مصارفها، وطرق اكتسابها، وطرق إنفاقها. الزكاة تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار. شرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس، وتطيب القلوب، وتنشرح الصدور، وينعم الجميع بالأمن والمحبة والأخوة. والزكاة تزيد في حسنات مؤديها، وتقي المال من الآفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع الجراثيم المالية كالسرقات، والنهب، والسطو
[1 – Makna Zakat, Hukumnya, dan Keutamaannya ]
Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk ibadah bagi hamba-Nya. Ada ibadah yang berkaitan dengan fisik seperti shalat, ada yang berkaitan dengan pengeluaran harta yang dicintai seperti zakat dan sedekah, ada pula yang mencakup fisik sekaligus harta seperti haji dan jihad, serta ada yang berkaitan dengan menahan diri dari hal-hal yang disukai dan diinginkan seperti puasa. Allah menetapkan keberagaman ibadah ini sebagai ujian bagi manusia, untuk melihat siapa yang lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabb-nya dibanding hawa nafsunya, serta agar setiap orang dapat melaksanakan ibadah yang lebih mudah baginya sesuai dengan kemampuannya.
Harta tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali jika memenuhi tiga syarat:
Harta tersebut harus halal. Harta itu tidak boleh melalaikan pemiliknya dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemiliknya harus menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Zakat
Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan dan peningkatan. Secara istilah, zakat adalah hak wajib yang harus ditunaikan dari harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
Zakat telah diwajibkan sejak di Mekah, namun ketentuan mengenai kadar nisab, jenis harta yang wajib dizakati, serta golongan penerima zakat ditetapkan di Madinah pada tahun kedua hijriah.
Hukum Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat dan shalat, serta merupakan rukun ketiga dalam Islam. Allah SWT berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)
Hikmah Disyariatkannya Zakat
Tujuan utama dari zakat bukan sekadar mengumpulkan harta dan membagikannya kepada fakir miskin, melainkan lebih dari itu, yaitu mengangkat derajat manusia agar tidak diperbudak oleh harta. Dengan demikian, zakat menyucikan baik pemberi maupun penerimanya.
Meskipun secara lahiriah zakat tampak mengurangi jumlah harta, hakikatnya ia justru mendatangkan keberkahan dan pertumbuhan harta, baik secara jumlah maupun nilai keberkahannya. Zakat juga meningkatkan keimanan dalam hati orang yang menunaikannya, menumbuhkan akhlak mulia, serta melatih seseorang untuk memberikan sesuatu yang dicintai demi mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yaitu keridhaan Allah SWT dan surga-Nya.
Sistem keuangan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa kepemilikan mutlak atas harta adalah milik Allah SWT. Hanya Allah yang berhak mengatur hukum kepemilikan, menetapkan kewajiban dalam harta, serta menentukan penggunaannya, cara memperolehnya, dan cara membelanjakannya.
Zakat juga berfungsi sebagai penebus dosa, penyebab masuk surga, serta penyelamat dari api neraka. Allah mensyariatkan zakat dan mendorong umat Islam untuk menunaikannya karena zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Selain itu, zakat menjadi jembatan yang menghubungkan antara orang kaya dan fakir miskin, sehingga hati menjadi bersih, jiwa merasa tenteram, dada menjadi lapang, serta menciptakan keamanan, kasih sayang, dan persaudaraan dalam masyarakat.
Zakat menambah pahala orang yang menunaikannya, melindungi harta dari berbagai bencana, menyuburkan dan mengembangkannya, serta menutupi kebutuhan fakir miskin. Zakat juga menjadi sarana untuk mengatasi masalah kejahatan ekonomi seperti pencurian, perampokan, dan perampasan.
فقه الزكاة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الجزء الأول
مَعْنَى الصَّدَقَةِ: وَالزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ تُسَمَّى فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ “صَدَقَةً”، حَتَّى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: “الصَّدَقَةُ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ، يَفْتَرِقُ الِاسْمُ وَيَتَّفِقُ الْمُسَمَّى ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْحَادِي عَشَرَ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ). قَالَ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التَّوْبَةُ: ١٠٣). مَعْنَى الصَّدَقَةِ: وَالزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ تُسَمَّى فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ “صَدَقَةً”، حَتَّى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: “الصَّدَقَةُ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ، يَفْتَرِقُ الِاسْمُ وَيَتَّفِقُ الْمُسَمَّى ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْحَادِي عَشَرَ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ). قَالَ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التَّوْبَةُ: ١٠٣). وَقَالَ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (التَّوْبَةُ: ٥٨). وَقَالَ: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. الْآيَةَ (التَّوْبَةُ: ٦٠). إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ ذَكَرَ أُسْتَاذُنَا الْمَرْحُومُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ يُوسُفَ مُوسَى فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى “شَاخْتَ” فِي دَائِرَةِ الْمَعَارِفِ أَنَّ الْقُرْآنَ أَشَارَ أَوَّلًا إِلَى الزَّكَاةِ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ لَفْظَةَ الزَّكَاةِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَتَأَمَّلُ الْقُرْآنَ الْمَكِّيَّ يَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَةَ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْقُرْآنُ أَوَّلًا هِيَ الزَّكَاةُ وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَخْدِمُ كَلِمَةَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَاتِ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ). وَفِي الْحَدِيثِ: “لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ” (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. وَسَيَأْتِي). وَفِي حَدِيثِ إِرْسَالِ مُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ: “أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ”. وَهَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا قَدْ جَاءَتْ فِي شَأْنِ الزَّكَاةِ عَبَّرَتْ عَنْهَا بِالصَّدَقَةِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ مُصَدِّقًا لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الصَّدَقَاتِ وَيُفَرِّقُهَا. بَيْدَ أَنَّ الْعُرْفَ قَدْ ظَلَمَ كَلِمَةَ الصَّدَقَةِ، وَأَصْبَحَتْ عُنْوَانًا عَلَى التَّطَوُّعِ وَمَا تَجُودُ بِهِ النَّفْسُ عَلَى مِثْلِ الْمُتَسَوِّلِينَ وَالشَّحَّاذِينَ. وَلَكِنَّ الْمَدْلُولَاتِ الْعُرْفِيَّةَ يَجِبُ أَنْ لَا تَخْدَعَنَا عَنْ حَقَائِقِ الْكَلِمَاتِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ فِي عَهْدِ نُزُولِ الْقُرْآنِ، وَمَادَّةُ الصَّدَقَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الصِّدْقِ. وَلِلْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ كَلَامٌ قَيِّمٌ فِي مَعْنَى تَسْمِيَةِ الزَّكَاةِ صَدَقَةً، قَالَ: “وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي مُسَاوَاةِ الْفِعْلِ لِلْقَوْلِ وَالِاعْتِقَادِ”.
Makna Sedekah:
Zakat secara syar’i dalam bahasa Al-Qur’an dan Sunnah terkadang disebut dengan “sedekah”. Hingga Imam Al-Mawardi berkata “Sedekah adalah zakat, dan zakat adalah sedekah. Nama berbeda, tetapi maknanya sama. Hal ini disebutkannya dalam awal Bab Kesebelas tentang Wilayah Sedekah dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Allah Ta’ala berfirman:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (At-Taubah: 103) Allah juga berfirman: “Di antara mereka ada yang mencelamu dalam pembagian sedekah, jika mereka diberi sebagian darinya, mereka rela. Tetapi jika tidak diberi, mereka marah” (At-Taubah: 58).Dan juga firman-Nya: “Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin…” (At-Taubah: 60).
Dalam Tafsir yang ditulis oleh guru kami yang telah wafat, Dr. Muhammad Yusuf Musa, saat mengomentari pendapat “Shacht” dalam Ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa Al-Qur’an awalnya menyebut zakat dengan istilah sedekah. Kemudian, ia menggunakan istilah zakat. Namun, jika kita merenungkan Al-Qur’an yang turun di Makkah, kita akan menemukan bahwa kata yang pertama kali digunakan adalah zakat. Hampir tidak ditemukan penggunaan kata sedekah atau shadaqat kecuali setelah turunnya ayat-ayat di Madinah.
Dalam hadits disebutkan: “Tidak ada kewajiban zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tentang pengutusan Mu’adz ke Yaman, Nabi bersabda: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”
Semua nash ini berbicara tentang zakat tetapi menggunakan istilah sedekah. Oleh karena itu, orang yang bertugas mengumpulkan zakat disebut mushaddiq karena ia mengumpulkan dan mendistribusikan shadaqat (sedekah). Namun, dalam pemahaman masyarakat, kata sedekah mengalami penyempitan makna dan hanya diidentikkan dengan pemberian sukarela kepada para peminta-minta dan fakir miskin. Padahal, makna bahasa aslinya dalam era turunnya Al-Qur’an tidak terbatas pada itu.
Secara etimologis, kata sedekah berasal dari akar kata shidq (kejujuran), sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi: “Makna penamaan zakat dengan sedekah diambil dari sifat jujur (shidq) dalam kesesuaian antara perbuatan, ucapan, dan keyakinan
وَبِنَاءُ “صَدَقَ” يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَعَضْدِهِ بِهِ، وَمِنْهُ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ، أَيْ تَحْقِيقُ الْحِلِّ وَتَصْدِيقُهُ بِإِيجَابِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ. وَيَخْتَلِفُ كُلُّهُ بِتَصْرِيفِ الْفِعْلِ، يُقَالُ صَدَقَ فِي الْقَوْلِ صَدَاقًا وَتَصْدِيقًا، وَتَصَدَّقْتُ بِالْمَالِ تَصَدُّقًا، وَأَصْدَقْتُ الْمَرْأَةَ إِصْدَاقًا، وَأَرَادُوا بِاخْتِلَافِ الْفِعْلِ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمَعْنَى الْمُخْتَصِّ بِهِ فِي الْكُلِّ، وَمُشَابَهَةُ الصِّدْقِ هُنَا لِلصَّدَقَةِ أَنَّ مَنْ أَيْقَنَ مِنْ دِينِهِ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْمَصِيرُ، وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَنْطَرَةٌ إِلَى الْآخِرَةِ، وَبَابٌ إِلَى السُّوءِ أَوِ الْحُسْنَى – عَمِلَ لَهَا، وَقَدَّمَ مَا يَجِدُهُ فِيهَا، فَإِنْ شَكَّ فِيهَا أَوْ تَكَاسَلَ عَنْهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا – بَخِلَ بِمَالِهِ وَاسْتَعَدَّ لِآمَالِهِ، وَغَفَلَ عَنْ مَآلِهِ” (أَحْكَامُ الْقُرْآنِ – الْقِسْمُ الثَّانِي ص ٩٤٦ بِتَحْقِيقِ الْبَجَاوِيِّ) أَقُولُ: وَلِهَذَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الْإِعْطَاءِ وَالتَّصْدِيقِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْبُخْلِ وَالتَّكْذِيبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (اللَّيْلِ:٥-١٠). فَالصَّدَقَةُ إِذَنْ دَلِيلُ الصِّدْقِ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ” (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ).
الزَّكَاةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
وَقَدْ تَكَرَّرَتْ كَلِمَةُ الزَّكَاةِ مُعَرَّفَةً إِنَّمَا قُلْنَا مُعَرَّفَةً، لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مُنَكَّرَةً فِي آيَتَيْنِ بِمَعْنَى آخَرَ: (خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً) (الْكَهْفُ: ٨١) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً) (مَرْيَمُ: ١٣) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٣٠) ثَلَاثِينَ مَرَّةً، ذُكِرَتْ فِي (٢٧) سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا مُقْتَرِنَةً بِالصَّلَاةِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ذُكِرَتْ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ مَعَ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي آيَتِهَا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) (الْمُؤْمِنُونَ: ٤) .. بَعْدَ آيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (الْمُؤْمِنُونَ:٢).
Makna “Shadaqa” dan Hubungannya dengan Shadaqah
Kata kerja “shadaqa” merujuk pada merealisasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menguatkannya dengannya. Dari sini berasal istilah “shadaq” (mahar perempuan), yaitu realisasi dan penegasan kehalalan melalui pemberian harta dan akad nikah dengan cara yang disyariatkan. Makna ini bervariasi tergantung bentukt perubahannya dalam bahasa Arab. Dikatakan shadaqa dalam perkataan dengan makna “shadaqan” dan”tasdiqan” (membenarkan). Seseorang yang bersedekah dengan harta disebut tasaddaqtu dengan makna”tasaddaqan” (bersedekah). Sementara itu, seseorang yang memberikan mahar kepada perempuan dikatakan asdaqtu dengan makna “ishdaqan” (memberikan mahar).
Perbedaan dalam bentuk kata kerja ini menunjukkan makna khusus yang terkandung dalam setiap pemakaian. Kesamaan antara shidq (kejujuran) dan shadaqah (sedekah) adalah bahwa seseorang yang meyakini dengan benar ajaran agamanya—bahwa kebangkitan di akhirat adalah hakikat, bahwa negeri akhirat adalah tempat kembali, dan bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat serta gerbang menuju kebahagiaan atau kesengsaraan—akan beramal sesuai keyakinannya. Ia akan mendahulukan amal yang akan ditemuinya di akhirat. Namun, jika seseorang meragukannya, bermalas-malasan dalam beramal, atau lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka ia akan bersikap kikir terhadap hartanya, mempersiapkan ambisi duniawinya, dan lalai terhadap akhir hidupnya. Oleh karena itu, Allah menggabungkan antara memberi dan membenarkan,sebagaimana Dia juga menggabungkan antara sifat kikir dan mendustakan dalam firman-Nya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka Kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan.” (QS. Al-Lail: 5-10)
Dengan demikian, sedekah merupakan bukti kejujuran iman dan keyakinan terhadap Hari Pembalasan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:”Sedekah adalah bukti (keimanan).” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)
Zakat dalam Al-Qur’an : Kata “zakat” dalam Al-Qur’an sering kali disebut dalam bentuk ma’rifah (dengan alif-lam), kecuali dalam dua ayat di mana ia disebut dalam bentuk nakirah (tanpa alif-lam) dengan makna yang berbeda: (Sesuatu) yang lebih baik darinya dalam hal kesucian (zakat) – (QS. Al-Kahfi: 81) Dan kasih sayang dari Kami serta kesucian (zakat) – (QS. Maryam: 13) Dalam Al-Qur’an, kata “zakat” disebut sebanyak 30 kali, dengan 27 kali di antaranya disebut bersama dengan shalat dalam satu ayat. Dalam satu tempat lainnya, zakat disebut dalam satu rangkaian dengan shalat, meskipun tidak dalam ayat yang sama, yaitu dalam firman Allah: “Dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS. Al-Mu’minun: 4) .Ayat ini datang satu ayat setelah firman-Nya: “Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.” (QS. Al-Mu’minun: 2)
وَالْمُتَتَبِّعُ لِلْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِينَ الَّتِي ذُكِرَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ يَجِدُ أَنَّ (٨) ثَمَانِيَةً مِنْهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ وَسَائِرُهَا فِي السُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ (رَاجِعْ الْمُعْجَمَ الْمُفَهْرَسَ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: كَلِمَةُ الزَّكَاةِ لِلْأُسْتَاذِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي). وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ أَنَّ الزَّكَاةَ قُرِنَتْ بِالصَّلَاةِ فِي (٨٢) اِثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مَوْضِعًا مِنْ الْقُرْآنِ كَذَا فِي “الدُّرِّ الْمُخْتَارِ” وَ”الْبَحْرِ” وَ”النَّهْرِ” وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ، وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ رَدَّ الْمُحْتَارِ تَصْوِيبَهُ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ اقْتِرَانَهَا بِالصَّلَاةِ فِي (٢٨) مَوْضِعًا فَقَطْ… وَلَعَلَّ الْمُصَوِّبَ أَرَادَ عَدَدَ مَرَّاتِ وُرُودِهَا كُلِّهَا مَعْرِفَةً وَمُنَكَّرَةً، وَهُوَ عَدَدٌ مُبَالَغٌ فِيهِ وَيَرُدُّهُ الْإِحْصَاءُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، حَتَّى لَوْ قَالُوا: الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِثْلُ “الْإِنْفَاقِ” وَ”الْمَاعُونِ” وَ”طَعَامِ الْمِسْكِينِ” وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يَجْتَمِعْ لَنَا هَذَا الْعَدَدُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَدَدَ مُحَرَّفٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ إِلَى اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ. أَمَّا كَلِمَةُ “الصَّدَقَةُ” وَ”الصَّدَقَاتُ” فَقَدْ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ الْمَدَنِيِّ.
Orang yang meneliti tiga puluh tempat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan zakat akan menemukan bahwa delapan di antaranya terdapat dalam surah-surah Makkiyah, sedangkan sisanya terdapat dalam surah-surah Madaniyah. (Lihat Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, kata “zakat”, karya Ustadz Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi).
Beberapa ulama menyebutkan bahwa zakat disebutkan bersama dengan shalat dalam delapan puluh dua (82) tempat dalam Al-Qur’an. Hal ini disebutkan dalam kitab Ad-Durr al-Mukhtar, Al-Bahr, An-Nahr, dan kitab-kitab fikih Hanafi lainnya. Namun, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar mengoreksi jumlah tersebut menjadi tiga puluh dua (32) tempat.
Pada kenyataannya, zakat disebutkan bersama dengan shalat hanya dalam dua puluh delapan (28) tempat. Mungkin orang yang mengoreksi tersebut bermaksud menghitung seluruh penyebutan kata “zakat” baik dalam bentuk ma’rifat maupun nakirah, tetapi jumlah tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disebutkan. Bahkan jika mereka memasukkan kata-kata yang berkaitan dengan zakat seperti “infaq”, “ma’un”, “thaa‘aam al-miskin” (makanan orang miskin), dan semisalnya, jumlah tersebut tetap tidak mencapai angka tersebut. Tampaknya jumlah yang benar telah terjadi kesalahan dalam penulisan dari tiga puluh dua (32) menjadi delapan puluh dua (82).
Adapun kata “shadaqah” dan “shadaqat” disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak dua belas (12) kali, dan semuanya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.
الموسوعة الفقهية الكويتيه ج١ص ٢٦١-٢٦٣
حكمة مشروعية الصدقة:
دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه رحمة بالضعفاء، ومواساة للفقراء، إلى جانب ما فيه من كسب الأجر، ومضاعفته، والتخلق بأخلاق الأنبياء، من البذل والإحسان.
حكم الصدقة:]
الصدقة سنة مستحبة كل وقت، وتتأكد في زمان وأحوال:
١ – فالزمان: كرمضان، وعشر ذي الحجة.
٢ – والحالات: أوقات الحاجة أفضل: دائمة كفصل الشتاء، أو طارئة كان تحدث مجاعة، أو جدب ونحو ذلك، وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح: من يضمر العداوة
فضل الصدقة:]
١ – قال الله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة/٢٧٤).
٢ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل)). متفق عليه (١). تسن صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق، وأهله، وأقاربه، وجيرانه، وخير صدقة تصدق بها المرء على نفسه وأهله، ويثبت أجر الصدقة وإن وقعت في يد غير أهلها. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وجهد المقل أفضل صدقة، وهو ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، ولها نصف الأجر، ويحرم إذا علمت أنه لا يرضى، فإن أذن لها فلها مثل أجره. الصدقة في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، وفي حال الشدة أفضل منها في حال الرخاء إذا قصد بها وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (٨) إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) (الإنسان/٨ – ٩).
النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع، وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة الواجبة، وتحل لهم صدقة التطوع.
تجوز صدقة التطوع على الكافر تأليفا لقلبه، وسدا لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر. يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية، لقول أم بجيد رضي الله عنها: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا، فادفعيه إليه في يده)). أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
Hikmah Pensyariatan Sedekah
Islam menganjurkan untuk berbagi dan mendorongnya sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang lemah serta kepedulian terhadap fakir miskin. Selain itu, sedekah juga menjadi sarana memperoleh pahala yang berlipat ganda dan meneladani akhlak para nabi, yaitu kedermawanan dan kebaikan.
Hukum Sedekah
Sedekah merupakan sunnah yang dianjurkan setiap waktu, namun lebih ditekankan pada waktu-waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu:
Dari sisi waktu: Seperti bulan Ramadan dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Dari sisi keadaan: Saat adanya kebutuhan lebih utama, baik kebutuhan yang bersifat tetap seperti musim dingin, maupun yang bersifat darurat seperti terjadi kelaparan atau kekeringan. Sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat yang memendam permusuhan (kasyih), yaitu orang yang menyimpan kebencian. Keutamaan Sedekah Allah berfirman: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 274) Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa bersedekah dengan sebiji kurma dari hasil usaha yang baik—dan Allah tidak menerima kecuali yang baik—maka Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya, hingga sedekah itu menjadi sebesar gunung.”(Muttafaqun ‘alaih) Hukum dan Ketentuan Sedekah Disunnahkan sedekah dari kelebihan nafkah diri dan orang yang menjadi tanggungannya, karena sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Orang yang paling berhak menerima sedekah adalah anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya, dan tetangganya. Sedekah terbaik adalah yang diberikan kepada diri sendiri dan keluarga. Pahala sedekah tetap diperoleh meskipun jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya. Sedekah terbaik adalah yang diberikan dari harta yang cukup, dan sedekah orang miskin yang melebihi kebutuhannya lebih utama. Seorang istri boleh bersedekah dari harta suaminya jika ia mengetahui kerelaannya, dan ia mendapatkan separuh pahala dari suaminya. Namun, jika ia tahu suaminya tidak ridha, maka sedekahnya haram. Jika suami mengizinkan, maka pahalanya sama dengan pahala suaminya. Sedekah di saat sehat lebih utama dibandingkan saat sakit, dan sedekah dalam kondisi sulit lebih utama dibandingkan dalam kondisi lapang, jika dilakukan dengan niat karena Allah. Allah berfirman: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu karena mengharap wajah Allah, kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu.” (QS. Al-Insan: 8-9) Rasulullah ﷺ tidak diperbolehkan menerima zakat wajib maupun sedekah sunnah. Demikian pula Bani Hasyim tidak boleh menerima zakat wajib, tetapi mereka boleh menerima sedekah sunnah. Diperbolehkan memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir untuk melunakkan hatinya atau untuk menghilangkan kelaparannya, dan seorang Muslim tetap mendapatkan pahala atas sedekah tersebut. Dalam setiap makhluk hidup terdapat pahala. Dianjurkan memberikan sesuatu kepada peminta-minta, meskipun jumlahnya kecil.
Dari Ummu Bujayd r.a., ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Ya Rasulullah, ada seorang miskin yang datang ke pintu rumahku, tetapi aku tidak memiliki apa pun untuk diberikan kepadanya.” Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika engkau tidak memiliki apa pun untuk diberikan kepadanya kecuali sepotong kaki kambing yang telah terbakar, maka berikanlah kepadanya.” (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)
تفسير البسيط الواحدى ج ٢ ص ٧٦
وقوله تعالى: {ينفقون} معنى الإنفاق في اللغة: إخراج المال من اليد. ومن هذا يقال: نفق المبيع إذا كثر مشتروه، فخرج عن يد البائع، ونفقت الدابة إذا خرجت روحها (٢)، والنفق (٣) سرب له مخلص إلى مكان آخر يخرج منه (٤)، والنافقاء من جحرة اليربوع: وهو الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق، لخروجه عن الإيمان بما ينطوي عليه من الكفر (٥).
والمراد بالإنفاق هاهنا: إنفاق فيما يكون طاعة فرضا أو نفلا؛ لأن الله تعالى مدحهم بهذا الإنفاق (٦).
٤ – قوله تعالى: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك}. قال مجاهد: الآيات الأربع من أول هذه السورة نزلت في جميع
المؤمنين (٧) سواء كانوا من العرب، أو من أهل الكتاب.
Dan firman Allah Ta’ala: {ينفقون} (mereka menginfakkan)—Makna infak dalam bahasa adalah mengeluarkan harta dari tangan. Dari makna ini juga dikatakan “نفق المبيع” (barang dagangan laris) jika banyak pembelinya, sehingga barang itu keluar dari tangan penjual. Juga dikatakan “نفقت الدابة” (hewan mati) jika ruhnya keluar.
Adapun “النفق” (terowongan), ia adalah lorong yang memiliki jalan keluar menuju tempat lain. “النافقاء” adalah salah satu lubang tempat tinggal hewan yurwa’ (sejenis gerbil gurun), yaitu lubang yang digunakan hewan tersebut untuk keluar jika ditangkap dari arah lain. Dari makna ini pula muncul istilah “المنافق” (munafik), karena ia keluar dari keimanan akibat kekufuran yang tersembunyi dalam dirinya.
Makna infak dalam ayat ini adalah menginfakkan harta dalam hal yang bernilai ketaatan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Sebab, Allah Ta’ala memuji mereka karena infak tersebut.
(4) Firman Allah Ta’ala: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك} (dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu).
Mujahid berkata: Empat ayat pertama dari surah ini turun mengenai seluruh kaum mukminin, baik dari kalangan bangsa Arab maupun Ahlul Kitab.
Penjelasan dari kutipan Tafsir al-Basith karya al-Wahidi ini membahas dua poin utama:
Makna”يُنْفِقُونَ” (menginfakkan)
Secara bahasa, infak berarti mengeluarkan sesuatu dari tangan. Contohnya: Nafaqa al-mabī‘ (نَفَقَ الْمَبِيعُ) artinya barang dagangan terjual laris karena keluar dari tangan penjual. Nafaqat ad-dābbah (نَفَقَتِ الدَّابَّةُ) artinya hewan mati karena ruhnya keluar dari tubuhnya. An-nafaq (النَّفَقُ) adalah sebuah terowongan yang memiliki jalan keluar ke tempat lain. An-nafiqā’ (النَّافِقَاءُ) adalah lubang khusus pada sarang hewan yurwa’ yang digunakan untuk keluar jika merasa terancam dari lubang lain.
Dari sini muncul istilah munafik (المنافق), yaitu seseorang yang secara lahiriah tampak beriman tetapi batinnya kufur, sebagaimana yurwa’ yang tampak di satu tempat tetapi keluar di tempat lain.
Makna infak dalam ayat ini merujuk pada pengeluaran harta dalam ketaatan kepada Allah, baik yang wajib (seperti infak kepada keluarga ) maupun sunnah (seperti infak fisabilillah). Allah memuji orang-orang yang berinfak karena perbuatan ini merupakan bagian dari keimanan yang benar.
Makna “وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ” (dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu)
Mujahid menafsirkan bahwa empat ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ini turun mengenai semua kaum mukminin, baik yang berasal dari bangsa Arab maupun Ahlul Kitab (orang-orang yang sebelumnya telah menerima wahyu seperti Yahudi dan Nasrani yang kemudian beriman kepada Islam).
Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan dua sifat utama orang-orang beriman yang dipuji oleh Allah:
Mereka berinfak di jalan Allah, baik dalam perkara wajib maupun sunnah. Mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, tanpa membeda-bedakan asal-usul mereka (baik dari kalangan Arab maupun Ahlul Kitab).
تفسير المنير الزحيلي ج٣ص٢٩٥-٢٩٦
{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأخرج عبد بن حميد والبزار عن ابن عمر قال:
حضرتني هذه الآية: {لن تنالوا البر}، فذكرت ما أعطاني الله تعالى فلم أجد أحب إلي من مرجانة (جارية رومية) فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله تعالى لنكحتها، فأنكحتها نافعا (مولاه الذي كان يحبه). ولم يمت ابن عمر إلا وأعتق ألف رقبة.
أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث: الجنة، أو العمل الصالح، أو الطاعة، والتقدير على المعنى الأول: لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون، وعلى المعنى الثاني: لن تصلوا إلى العمل الصالح… وعلى المعنى الثالث وهو معنى جامع: لن تصلوا إلى الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الحسن البصري: {حتى تنفقوا}: هي الزكاة المفروضة. والأولى أن يكون المراد كما قال الزمخشري: لن تبلغوا حقيقة البر حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها، كقوله: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة ٢٦٧/ ٢].
وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على أمرين:
الأول-أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب
الأموال وأفضلها عند مالكها، وبمقدار طيبها وحسنها يكون الثواب عليها.
الثاني-الترغيب والحث على إخفاء الصدقة، بعدا عن الرياء، وإخلاصا في العمل لوجه الله، وترفعا عن نفاذ الشيطان إلى قلب المؤمن الصالح.
انتهى الجزء الثالث ولله الحمد
Tafsir al-Munir, Jilid 27, Halaman 301-302
Kewajiban Berinfak dan Kepemilikan Allah atas Segala Sesuatu
Firman Allah: “Dan mengapa kalian tidak menginfakkan (harta) di jalan Allah, padahal milik Allah-lah warisan langit dan bumi?” (QS. Al-Hadid: 10). Maksudnya, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak berinfak di jalan Allah. Tidak perlu takut miskin, karena yang kalian infakkan adalah milik Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Semua harta yang ada pada kalian akan kembali kepada-Nya, sebagaimana warisan kembali kepada ahli waris. Jika kalian tidak menginfakkannya saat hidup, kalian akan kehilangan kesempatan itu.
Allah berfirman: “Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Saba’: 39 “Apa yang ada di sisi kalian akan habis, sedangkan apa yang ada di sisi Allah akan kekal.” (QS. An-Nahl: 96) Ayat ini menegaskan bahwa berinfak adalah keutamaan. Bahkan, semakin cepat seseorang berinfak, semakin tinggi derajatnya. Oleh karena itu, Allah berfirman: “Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum kemenangan dan berperang (bersama Rasulullah), mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang berinfak setelahnya dan berperang.”
Mereka yang berinfak sebelum Fathu Makkah lebih utama karena saat itu kaum Muslim masih sedikit dan membutuhkan bantuan. Sedangkan setelah Fathu Makkah, umat Islam semakin kuat dan rezeki semakin melimpah. Namun, Allah tetap menjanjikan pahala bagi kedua golongan tersebut: “Mereka semua dijanjikan pahala yang baik, dan Allah Maha Mengetahui segala yang kalian kerjakan.” Dalam hadits, Nabi ﷺ menegur Khalid bin Walid ketika ia berdebat dengan Abdurrahman bin ‘Auf. Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah kalian mencela para sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, kalian tidak akan mencapai keutamaan mereka walau setengahnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Pahala Berlipat bagi Orang yang Berinfak
Allah berfirman: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya dan ia akan mendapatkan pahala yang mulia.” Yakni, siapa yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas dan tanpa riya, maka Allah akan melipatgandakannya hingga tujuh ratus kali lipat atau lebih, tergantung keadaan dan keikhlasan orang tersebut.
Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, seorang sahabat bernama Abu Duhdah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kita?” Nabi ﷺ menjawab, “Ya.” Abu Duhdah pun berkata: “Aku telah meminjamkan kebunku kepada Allah.”
Kebun itu memiliki 600 pohon kurma, dan di dalamnya tinggal istri serta anak-anaknya. Ia pun mendatangi mereka dan berkata: “Keluarlah dari kebun ini, karena aku telah menyerahkannya kepada Allah.”
Tafsir al-Munir, Jilid 3, Halaman 295-296
Makna “Kalian Tidak Akan Meraih Kebajikan hingga Menginfakkan yang Kalian Cintai”
Ibnu Umar berkata: “Ketika ayat ini turun, aku melihat apa yang paling aku cintai dari hartaku. Aku tidak menemukan yang lebih aku cintai selain seorang budakku yang bernama Marjanah. Maka, aku pun membebaskannya karena Allah.”
Sebagian ulama mengatakan bahwa “al-birr” dalam ayat ini memiliki tiga tafsiran: Yaitu, Surga Amal saleh Ketaatan
Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa birr mencakup seluruh kebaikan, baik sedekah maupun bentuk ketaatan lainnya. Para ulama salaf, ketika mencintai sesuatu, mereka akan menyerahkannya kepada Allah.
Kesimpulan Hukum
Infak yang mendekatkan diri kepada Allah sebaiknya berasal dari harta yang paling dicintai oleh pemiliknya. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi lebih utama karena menghindari riya dan menjaga keikhlasan.
Selesai jilid ketiga, segala puji bagi Allah.
الموسوعة الفقهية الكويتيه ج٣ص ١٤٩-٢٥١
فضل النفقة:.✔
أحوال الإنفاق على الزوجة:✔
النفقة على الآباء والأولاد والأقارب:✔
أحوال المنفق:✔
[ فضل النفقة:]
١ – قال الله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة/٢٧٤).
٢ – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة)). متفق عليه (١).
٣ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار)). متفق عليه (٢).
[ أحوال الإنفاق على الزوجة:]
١ – نفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن ونحو ذلك بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين وعاداتهما.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم … – وفيه- ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله … ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). أخرجه مسلم (١).
٢ – يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها.
٣ – الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملا، فإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى.
٤ – لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن فعلى وارثه الموسر.
٥ – إذا نشزت المرأة أو حبست عنه سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملا.
إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى. إذا أعسر الزوج بالنفقة، أو الكسوة، أو السكن، أو غاب ولم يدع للزوجة نفقة وتعذر أخذها من ماله فلها الفسخ إن شاءت بإذن الحاكم.
[ النفقة على الآباء والأولاد والأقارب:]
تجب النفقة لأبويه وإن علوا حتى ذوي الأرحام منهم، وتقدم الأم على الأب في البر والنفقة، وتجب لولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم إن كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها.
١ – قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة/٢٣٣).
٢ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال: ((أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك)). متفق عليه (١).
تجب النفقة على كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. يشترط لوجوب النفقة على القريب من غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فقر المنفق عليه، غنى المنفق، عدم اختلاف الدين. يجب على السيد نفقة رقيقه المملوك، وإن طلب نكاحا زوجه سيده أو باعه، وإن طلبته أمة خير سيدها بين وطئها، أو تزويجها، أو بيعها. تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، ولا يجوز ذبحها للإراحة كالمريضة والكبيرة ونحوها، وعليه أن يقوم بما يلزمها.
[ أحوال المنفق:]
إن كان المنفق قليل المال وجب عليه أن يبدأ بالنفقات الواجبة من الزوجة، والفروع، والأصول، والمماليك فيبدأ بنفسه أولا، ثم من تجب نفقتهم مع العسر واليسر وهم: الزوجة، والمماليك، والبهائم.
ثم من تجب نفقتهما ولو لم يرثهم المنفق من الأصول، كالأم والأب، والفروع كالأولاد، ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب، أما إن كان المنفق غنيا فينفق على الجميع.
Keutamaan Nafkah Allah berfirman:
“Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 274) Dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika seorang Muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dengan mengharap pahala, maka itu menjadi sedekah baginya.” (Muttafaqun ‘alaih) Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan seorang janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid di jalan Allah atau seperti orang yang shalat malam dan berpuasa di siang hari.” (Muttafaqun ‘alaih) Ketentuan Nafkah kepada Istri Nafkah istri wajib ditanggung suami, mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang layak baginya, sesuai dengan kondisi zaman, negara, dan kebiasaan pasangan.
Dari Jabir bin Abdullah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan hubungan dengan mereka melalui kalimat Allah. Kewajiban kalian kepada mereka adalah memberikan rezeki dan pakaian dengan cara yang baik.” (HR. Muslim) Istri yang ditalak raj’i tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan giliran. Istri yang ditalak bain (baik karena fasakh maupun talak tiga) tetap mendapatkan nafkah jika sedang hamil. Jika tidak hamil, maka tidak berhak mendapatkan nafkah atau tempat tinggal. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah, kecuali jika sedang hamil. Dalam hal ini, nafkahnya diambil dari harta peninggalan untuk anak dalam kandungannya. Jika tidak ada harta peninggalan, maka nafkah ditanggung oleh ahli warisnya yang mampu. Jika istri membangkang atau dipenjara, maka nafkahnya tidak wajib diberikan, kecuali jika ia sedang hamil. Jika suami pergi dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia tetap berkewajiban membayar nafkah yang telah lalu. Jika suami tidak mampu menafkahi istri, atau ia pergi tanpa meninggalkan nafkah, maka istri berhak meminta fasakh (pembatalan pernikahan) melalui pengadilan. Ketentuan Nafkah kepada Orang Tua, Anak, dan Kerabat Nafkah kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah lanjut usia, hukumnya wajib, termasuk kepada kerabat dekat jika mereka fakir dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Ibu lebih berhak mendapatkan nafkah dibandingkan ayah. Anak wajib diberi nafkah oleh ayahnya, mencakup seluruh kebutuhannya. Nafkah wajib diberikan kepada semua orang yang berhak menerima warisan dari pemberi nafkah. Jika seseorang memiliki sedikit harta, ia harus mendahulukan nafkah istri, anak, orang tua, dan budaknya sebelum kerabat lainnya. Nafkah terhadap hewan peliharaan juga wajib, termasuk memberi makan, minum, dan merawatnya dengan baik. Jika pemiliknya tidak mampu, ia harus menjual, menyewakan, atau menyembelihnya jika termasuk hewan yang boleh dimakan. Wallahu a’lam